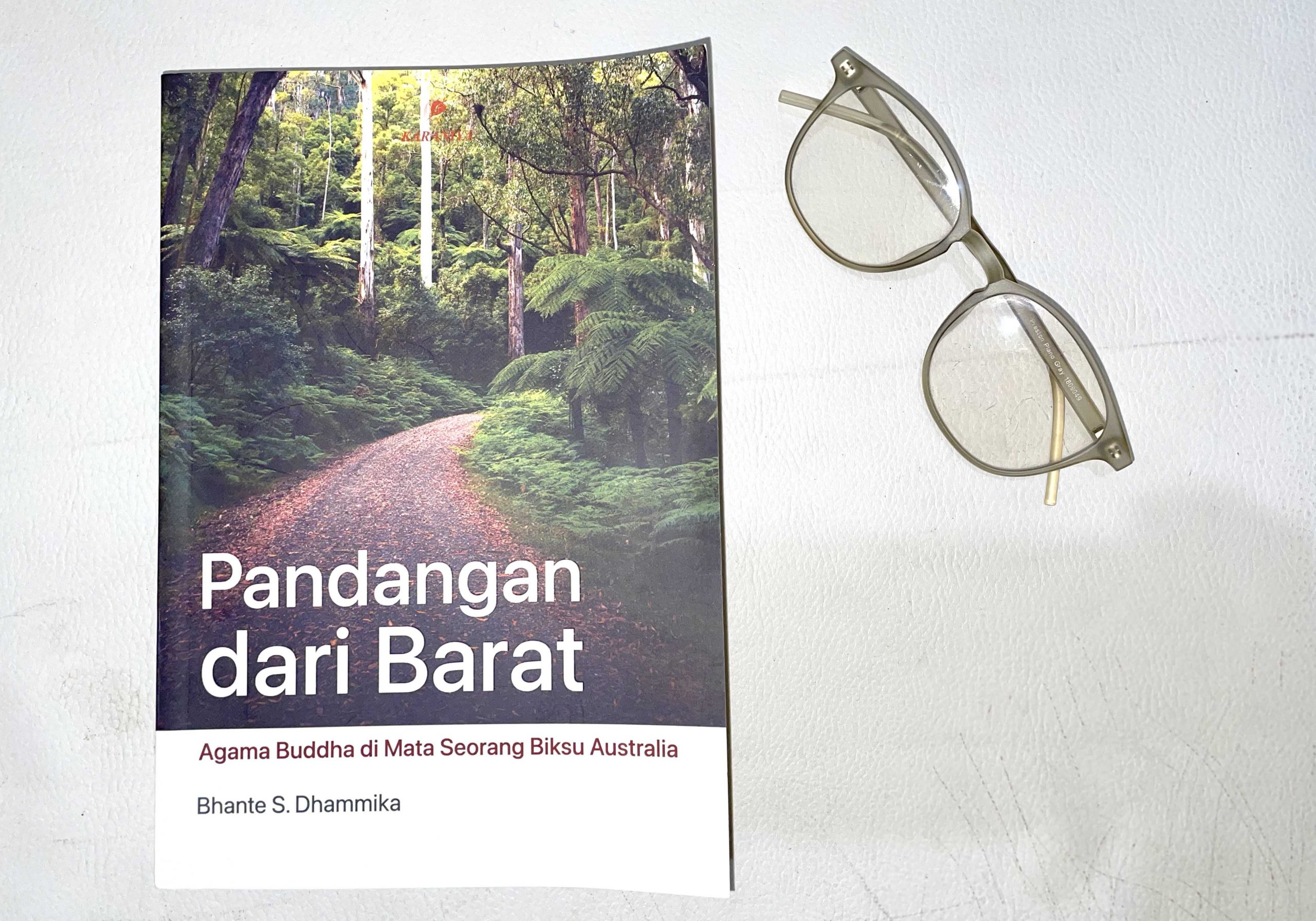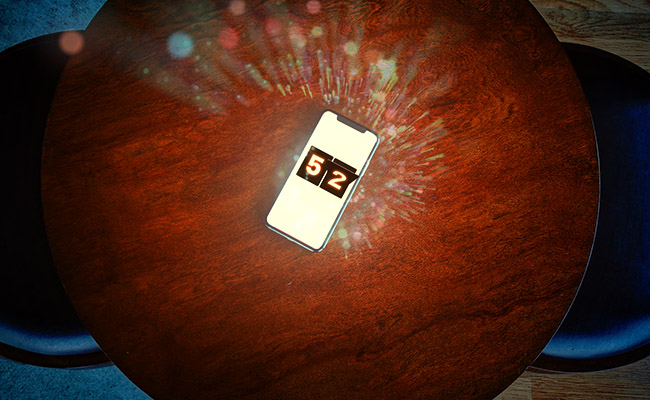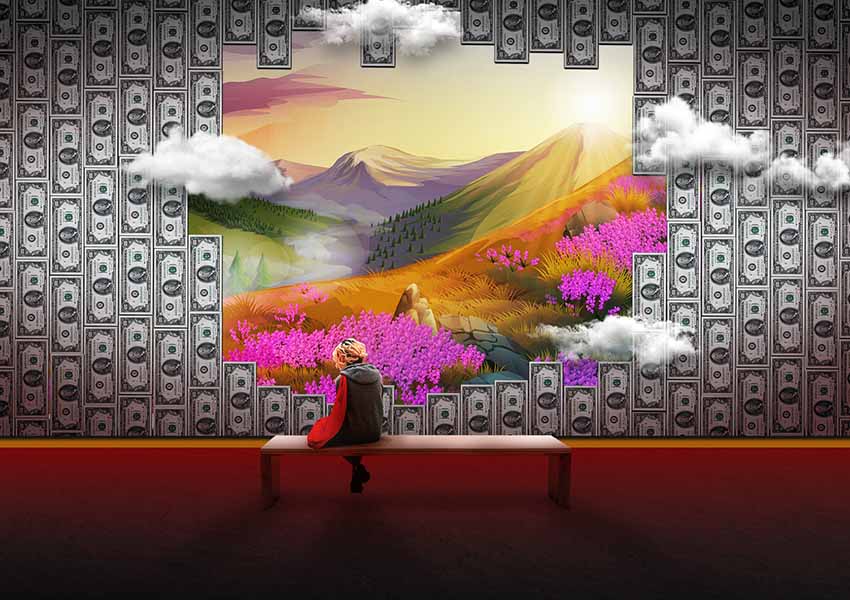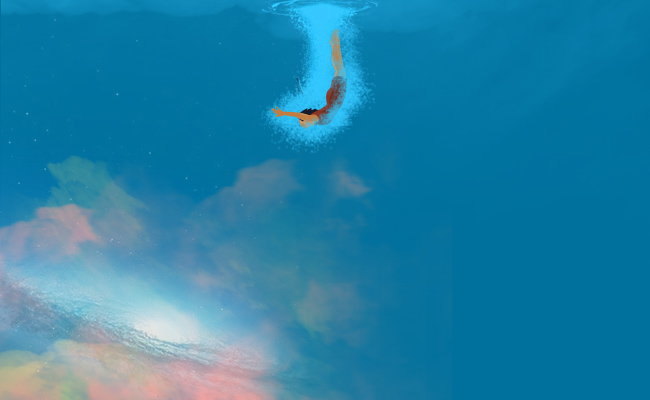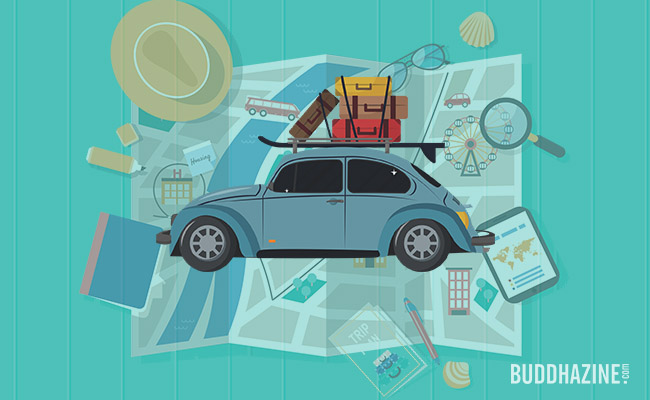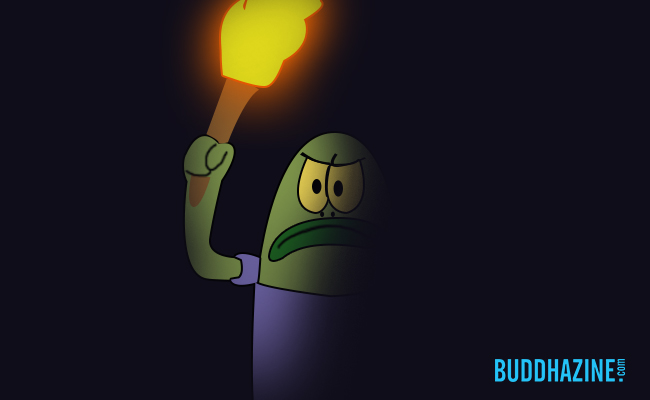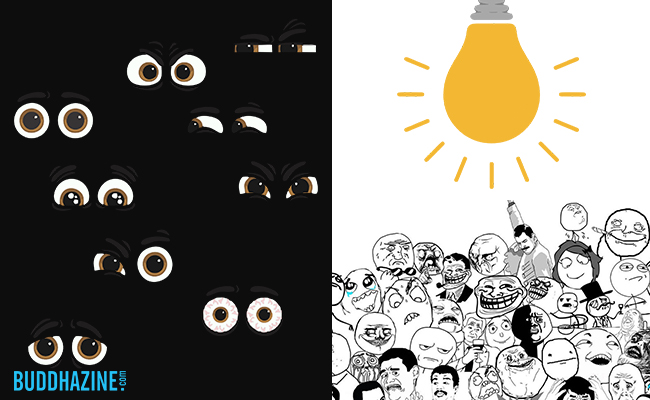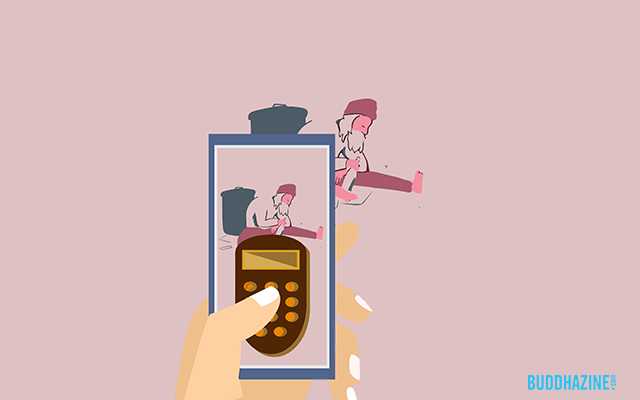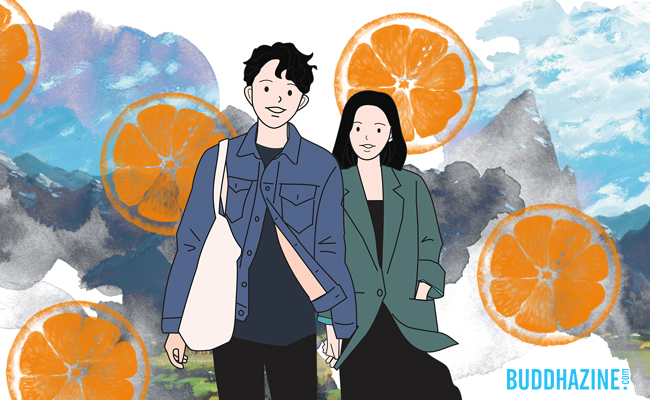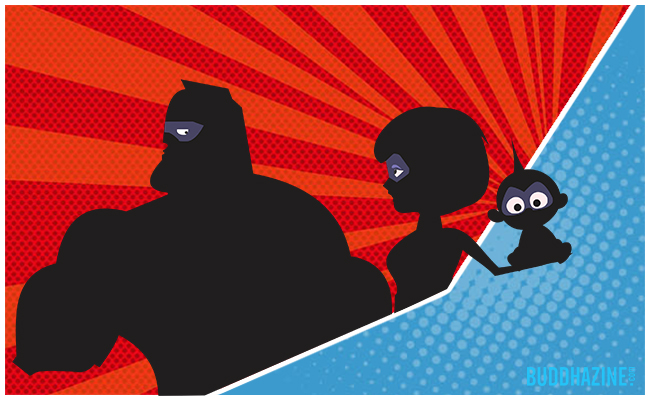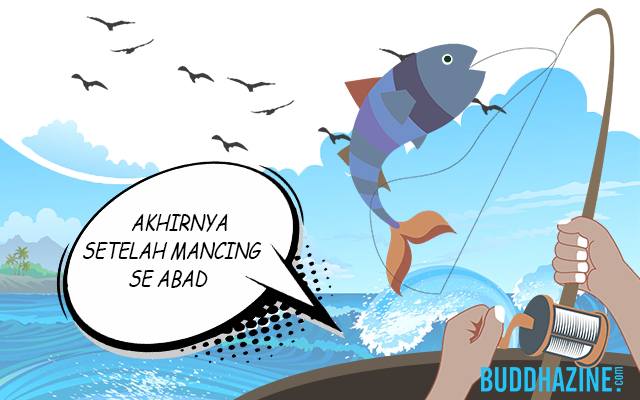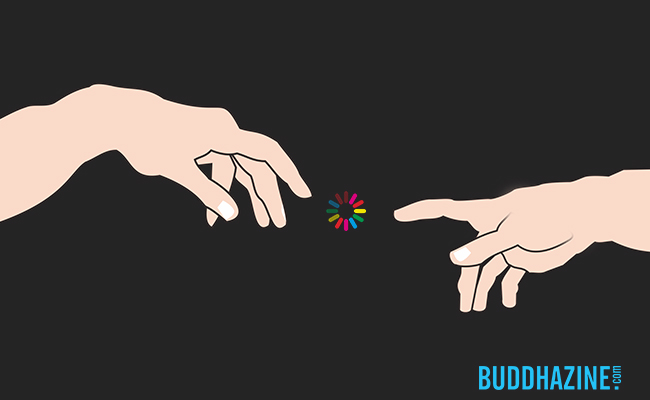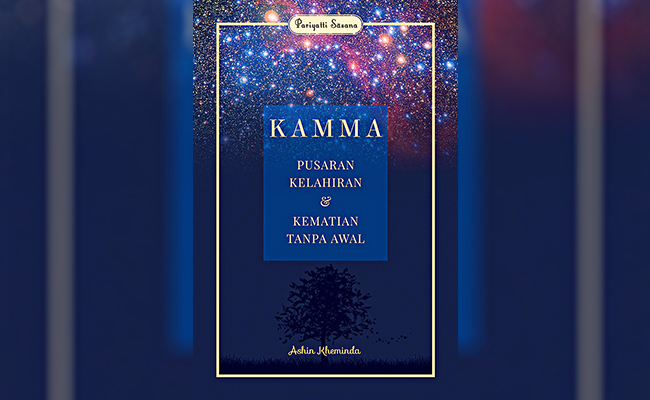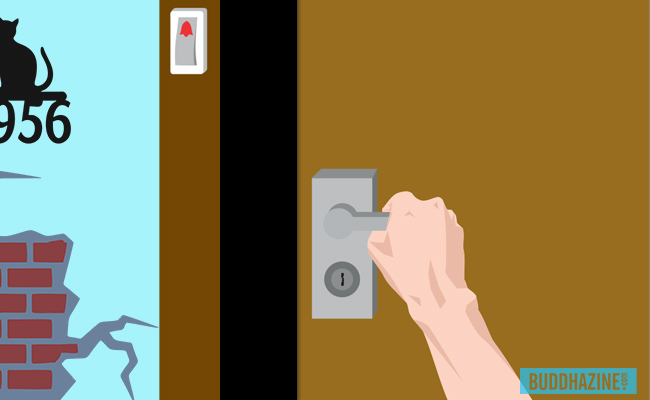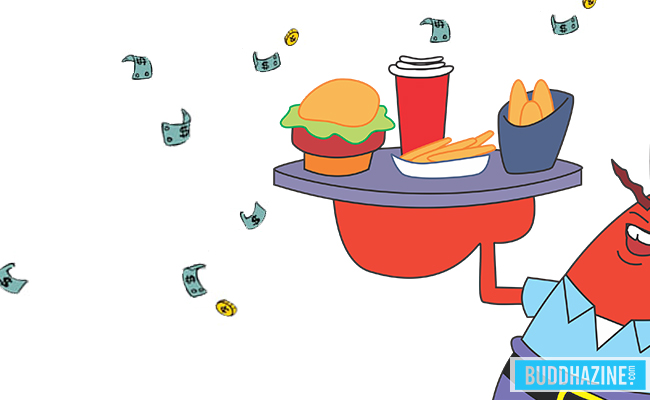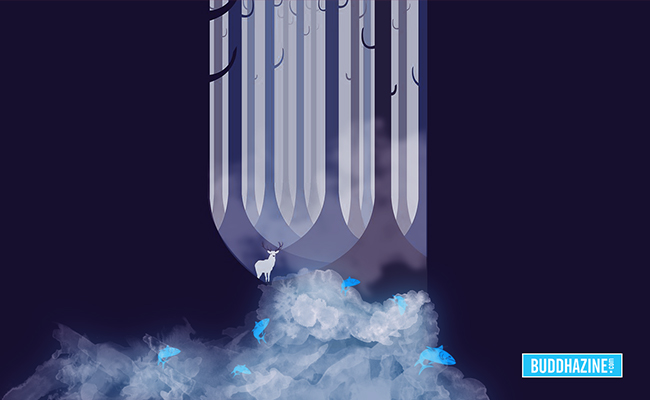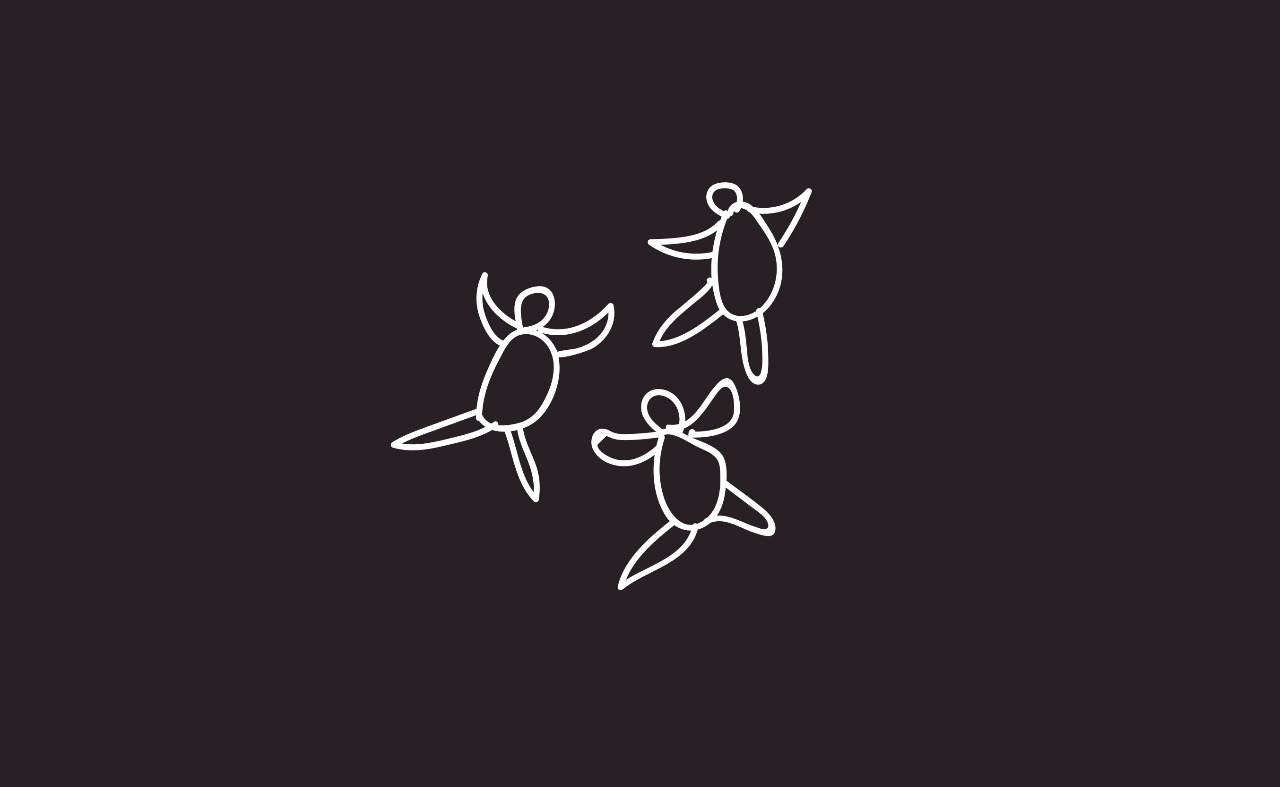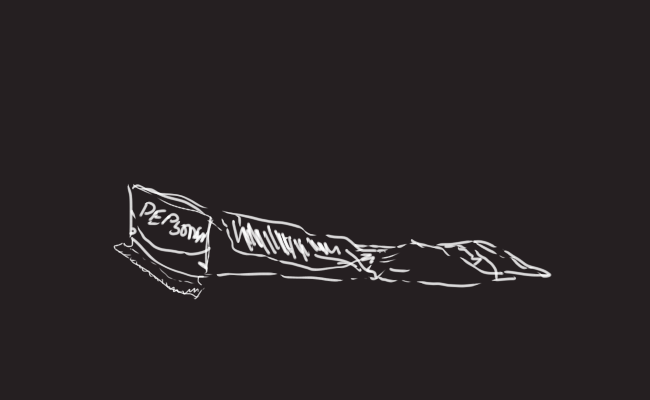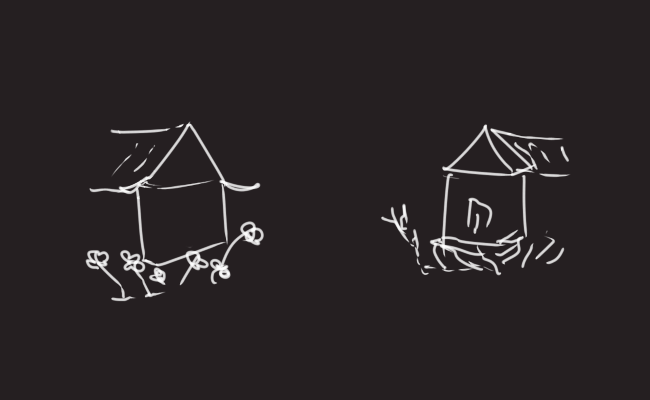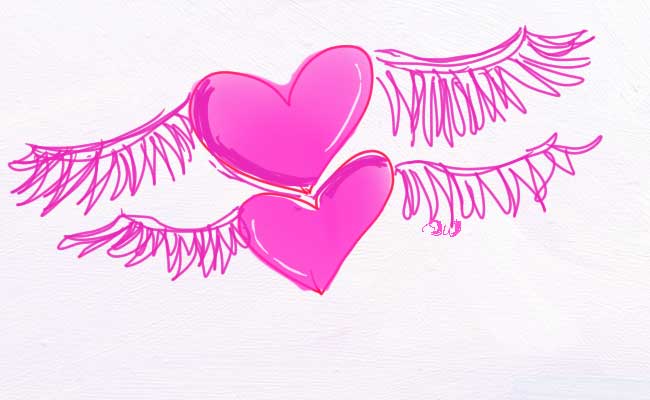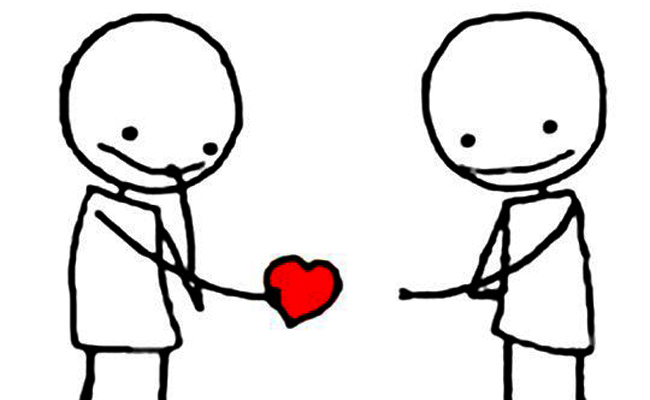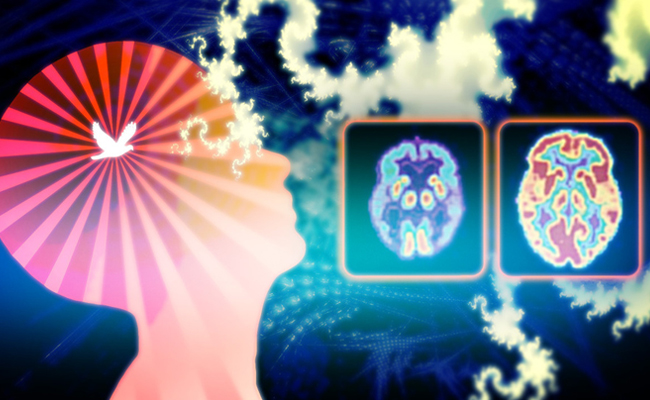Sembahyang arwah atau sering disebut Cioko di Indonesia merupakan salah satu tradisi orang Tionghoa di dunia. Festival yang jatuh pada pertengahan bulan ke-7 penanggalan lunar ini memperingati arwah leluhur yang telah meninggal dunia.
Menurut tradisi dan budaya Tionghoa, tanggal 15 bulan 7 adalah Hari Hantu dan bulan 7 secara umum dianggap sebagai Bulan Hantu dimana hantu – termasuk arwah leluhur kita, keluar dari alam neraka. Berbeda dengan Festival Qingming atau Chengbeng di mana kita mengunjungi makam leluhur, membersihkan makam, dan mendoakan mereka; pada Festival Cioko ini justru mereka yang telah meninggal akan mengunjungi kita.
Berakar dari Sutra Ullambana
Meskipun festival ini dilaksanakan oleh semua orang Tionghoa di dunia terlepas dari apapun agamanya, akar dari tradisi sembahyang arwah ini dapat ditelusuri hingga masa India Kuno. Tradisi ini sendiri berasal dari Sutra Ullambana – salah satu sutra Mahayana, yang menjelaskan tentang perjuangan Maha Moggallana untuk menemui arwah ibunya di alam peta.
Kala itu, Maha Moggallana – salah satu siswa utama Buddha, telah mencapai abhinna dan menggunakan kekuatan batinnya untuk mencari arwah ibunya. Mengetahui arwah ibunya terlahir di alam peta (hantu kelaparan), beliau mencoba memberikan bantuan dengan membagikan semangkuk nasi. Sayangnya, sebagai seorang peta, arwah ibu Moggallana tidak dapat memakan makanan tersebut yang langsung berubah menjadi bara api.
Moggallana pun kemudian memohon Buddha untuk membantunya. Buddha menjelaskan bahwa seseorang dapat mempersembahkan dana makanan kepada anggota Sangha pada masa pavarana (akhir musim hujan/vassa) yang biasanya jatuh pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan lunar. Jasa kebajikan ini akan disalurkan oleh para bhikkhu kepada mereka yang telah meninggal dunia.
Sedangkan menurut tradisi Theravada, akar tradisi penghormatan leluhur ini berasal dari naskah yang lebih tua dari Sutra Ullambana, yaitu Petavatthu – bagian dari Kitab Pali. Catatan di dalam Petavatthu mirip dengan cerita di Sutra Ullambana meskipun tokoh yang diceritakan adalah Sariputta, bukan Moggallana.
Bukan sekedar tradisi
Festival Sembahyang Arwah ini bukan saja sekedar tradisi tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Pertama, kita dapat menilik pada tujuan diadakannya sembahyang arwah yaitu mengurangi penderitaan para leluhur yang telah meninggal dunia dan terlahir di alam peta.
Selain memupuk rasa bakti dan penghormatan terhadap jasa-jasa orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia, tradisi ini juga dapat menumbuhkan rasa empati kita terhadap semua makhluk – bahkan yang sudah meninggal dunia.
Kedua, konsep persembahan makanan kepada hantu kelaparan atau peta merupakan salah satu ajaran buddhis yang terus dilestarikan dari masa kehidupan Buddha. Bahkan di dalam Sutta Tirokudda (Khotbah di Luar Dinding), Buddha sendiri menjelaskan bagaimana para arwah berdiri di luar dinding, di perempatan serta pertigaan jalan, kembali ke rumah mereka yang dahulu, dan menunggu di samping tiang gerbang rumah; berharap mendapatkan persembahan makanan dari sanak saudara yang masih hidup.
Bukan dengan ratap tangis atau kesedihan yang dapat menolong mereka. Tetapi hanya ketika persembahan diberikan dengan benar kepada Sangha, dana itu dapat disalurkan dan berguna bagi para arwah.
Ketiga, persembahan yang disalurkan ini melalui anggota Sangha. Dengan demikian, secara tidak langsung kita juga turut menyokong para bhikkhu/ni dalam upaya mereka mempraktekkan Buddhadhamma.
Di dalam Sutta Tirokudda juga dijelaskan bagaimana para bhikkhu dapat pula diberi kekuatan atas dana yang dipersembahkan. Jadi ini bagaikan berdana dengan tiga manfaat: manfaat bagi para leluhur yang telah meninggal, manfaat bagi para bhikkhu/ni, dan manfaat bagi kita yang telah melaksanakan penghormatan ini.
Terakhir, biasanya persembahan yang disajikan akan dibagikan kepada anggota keluarga maupun fakir miskin yang turut hadir di sekitar rumah. Dengan demikian, kita turut membantu orang lain yang mungkin membutuhkan. Oleh karena itu, festival ini sering pula disebut sembahyang rebutan.
Berbagai festival terkait lainnya
Mirip dengan Festival Cioko, beberapa bangsa di negara berbeda juga memiliki tradisi serupa. Sebagai contoh negara-negara Theravada di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang memiliki tradisi serupa yang berakar dari Petavatthu.
Di Kamboja, masyarakat memberikan penghormatan kepada arwah para leluhur selama 15 hari yang dikenal sebagai perayaan Pchum Ben. Di Laos, Festival Boun khao padap din juga berlangsung selama 2 pekan. Di Sri Lanka, upacara matakadanaya dilaksanakan pada hari ketujuh, bulan ketiga dan setahun kepergian seseorang yang meninggal dunia.
Sedangkan di negara-negara yang terpengaruh ajaran Buddha lainnya seperti Jepang dan Vietnam juga memiliki festival serupa. Di Jepang, Festival Obon/Bon digelar sebagai festival hantu di mana masyarakat mengunjungi makam dan memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Di Vietnam, festival ini disebut Tet Trung Nguyen.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara