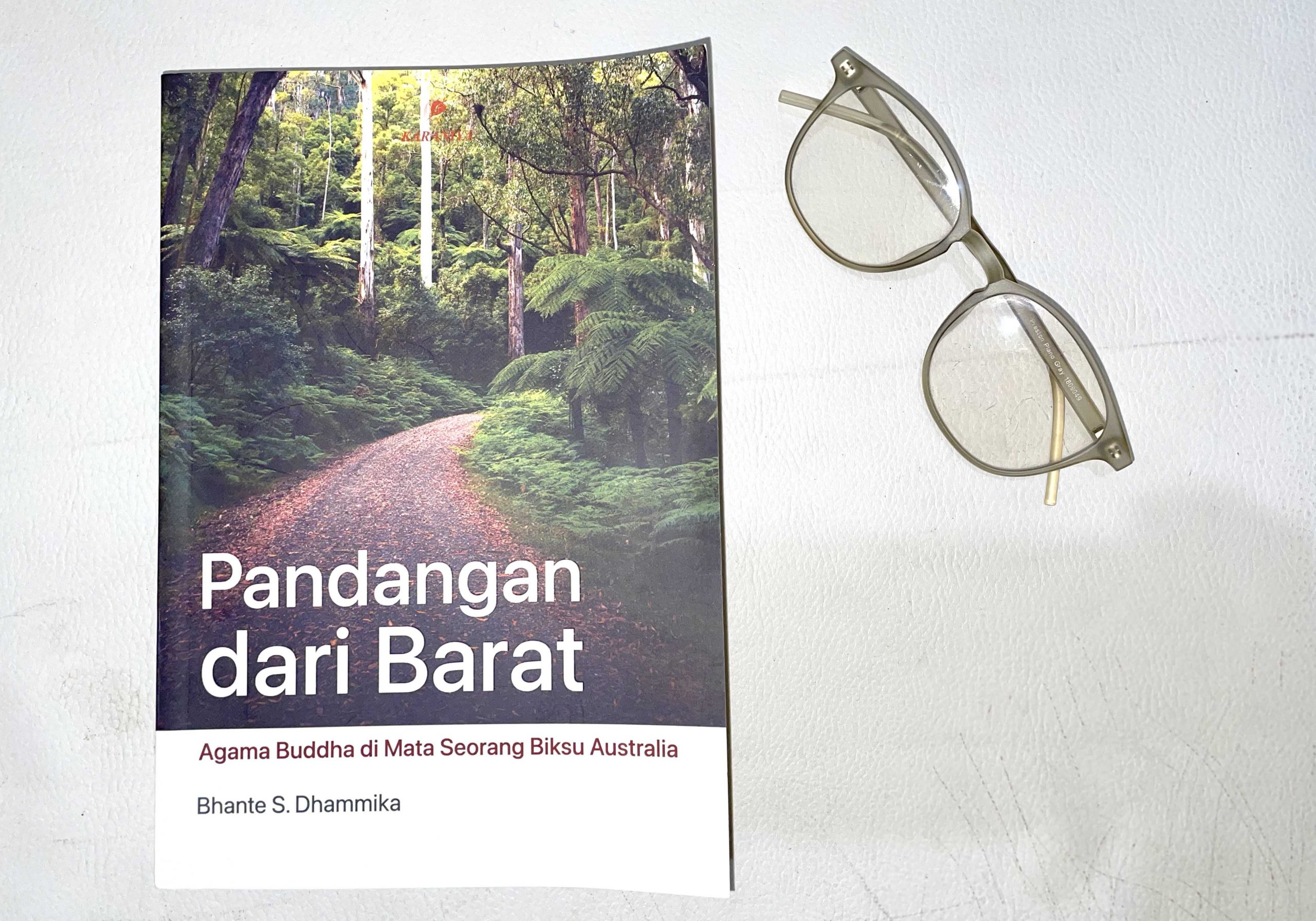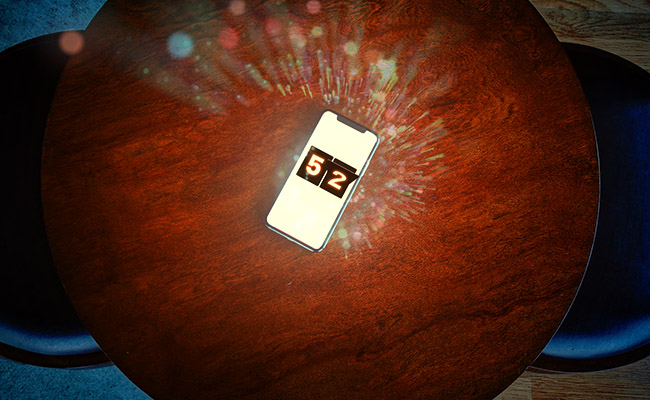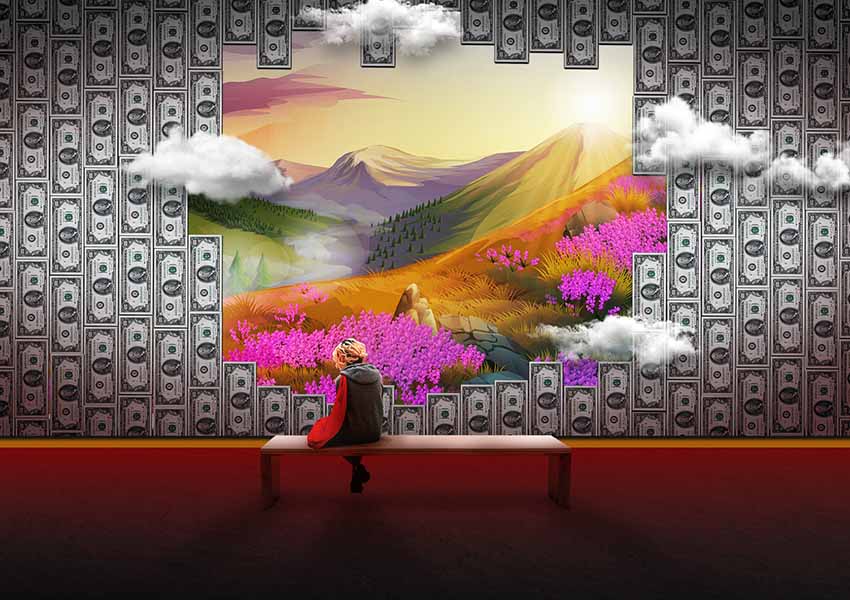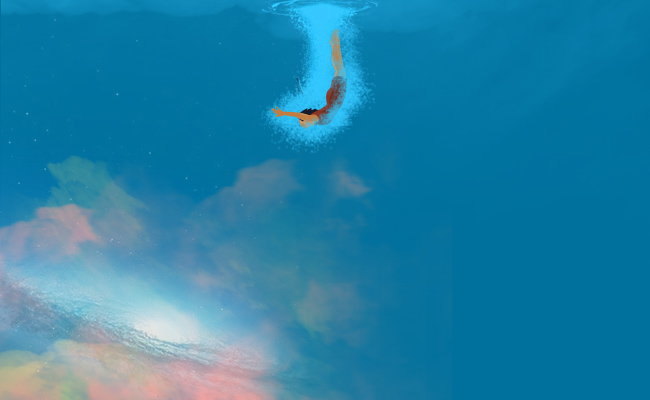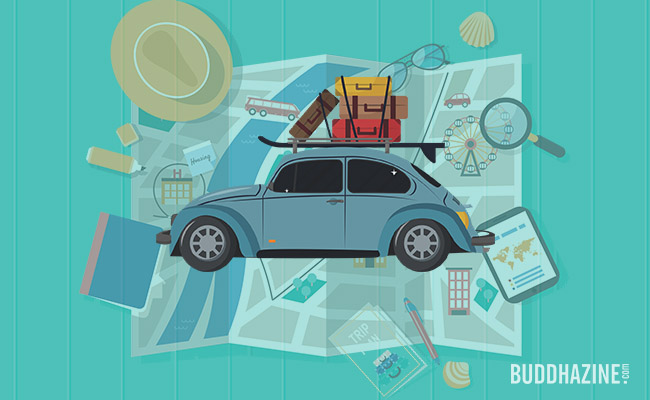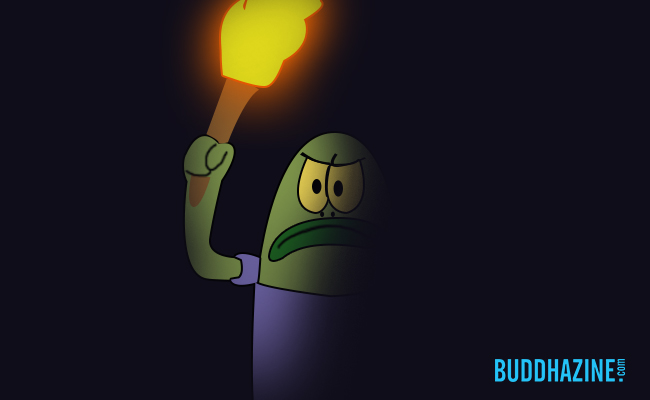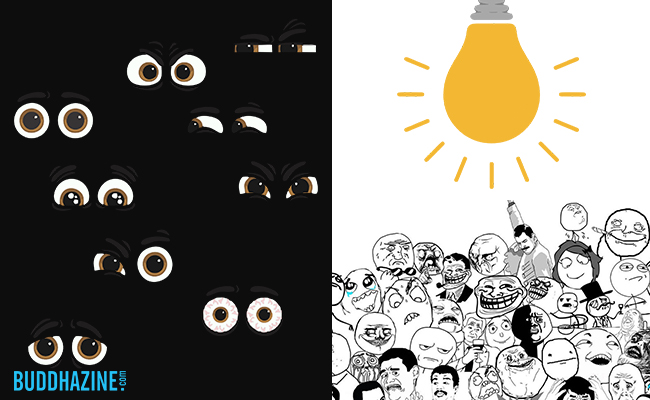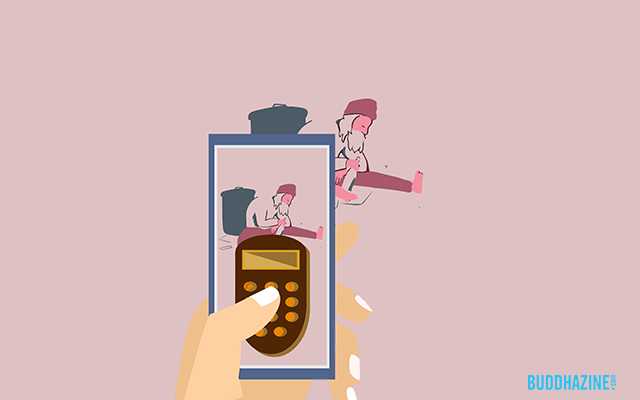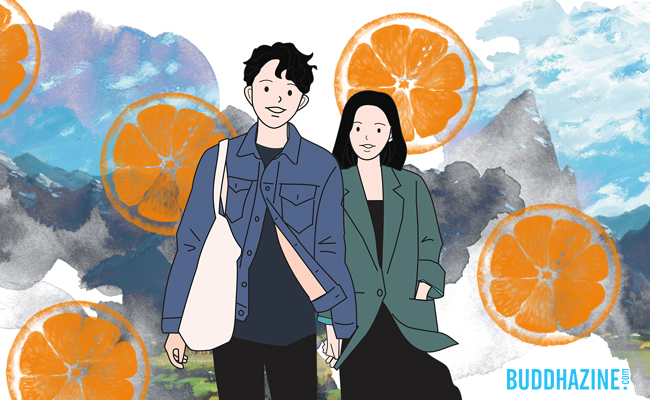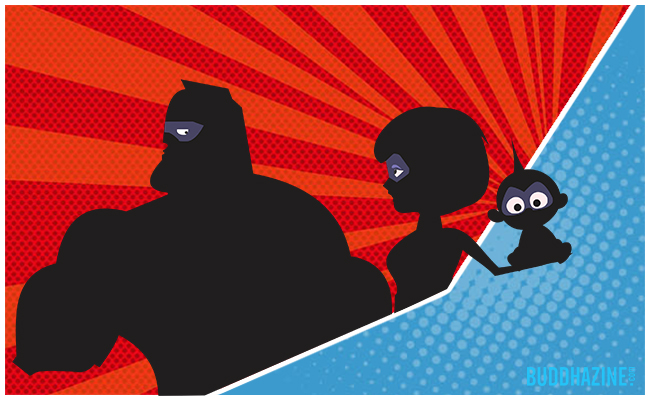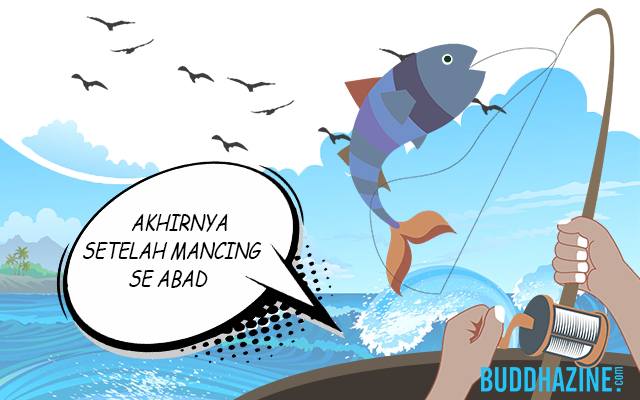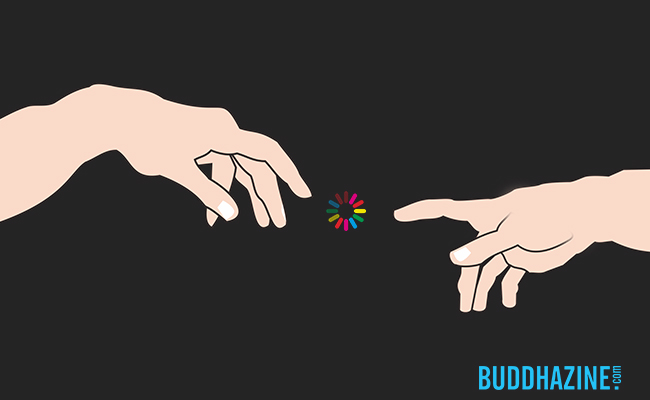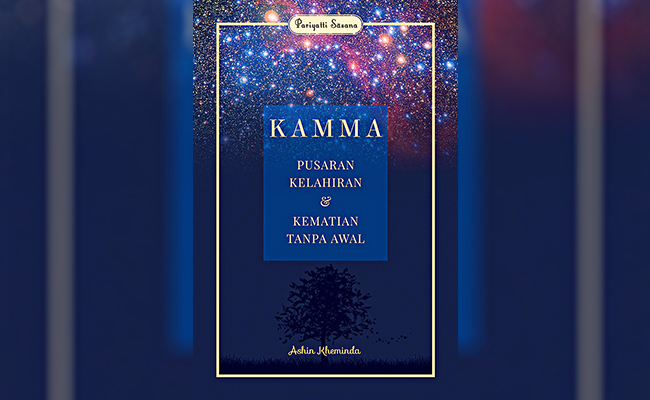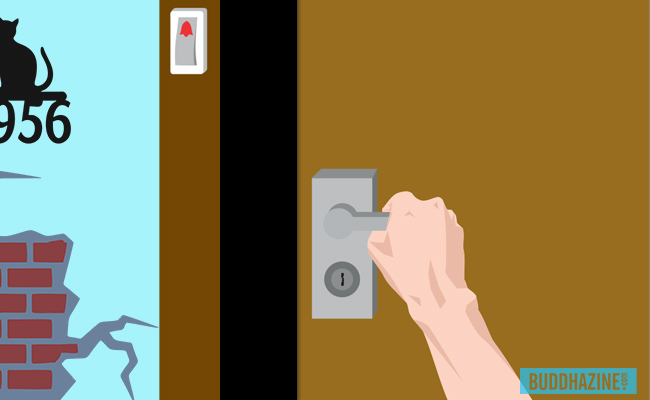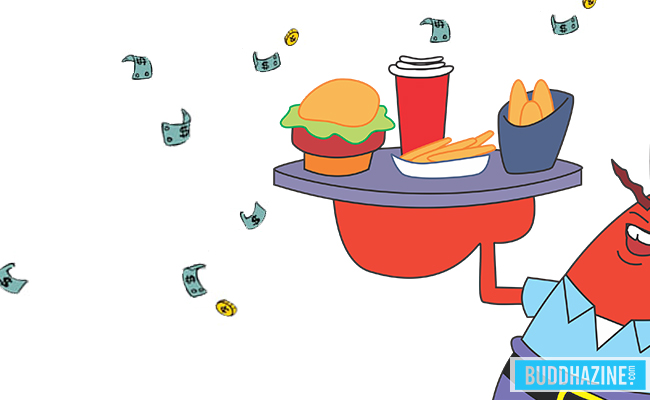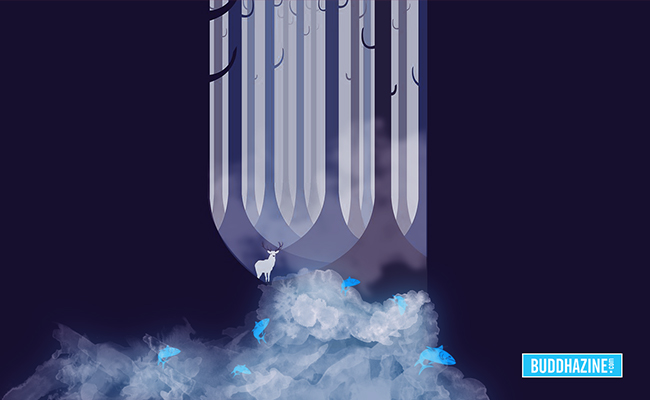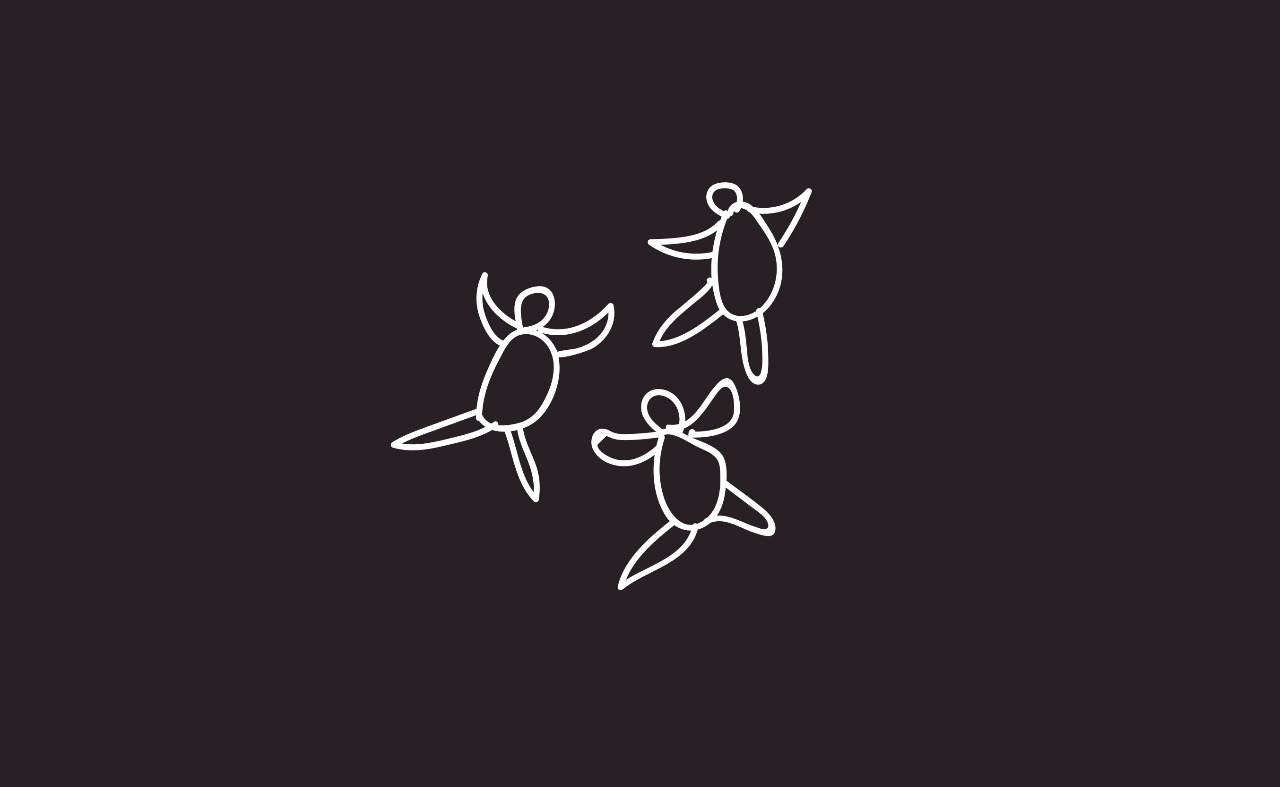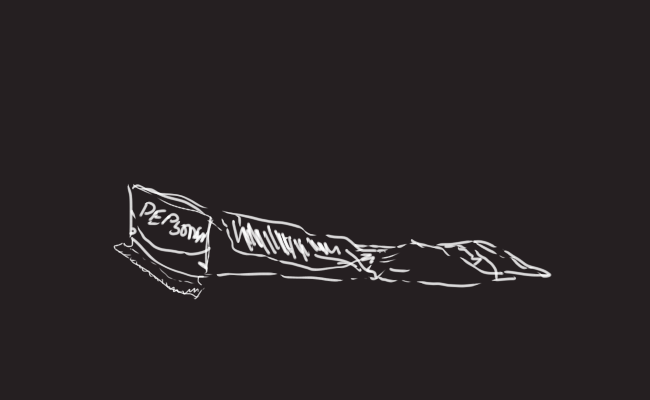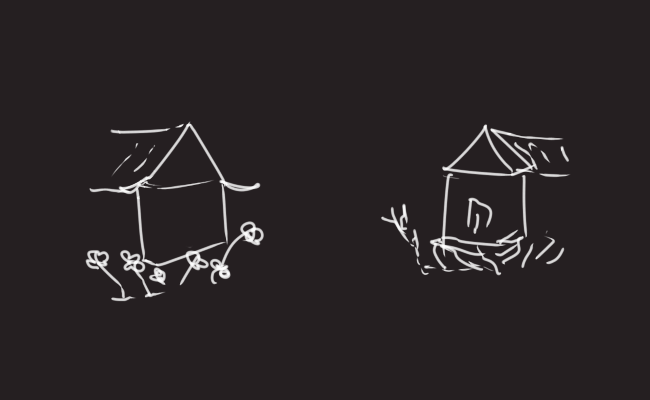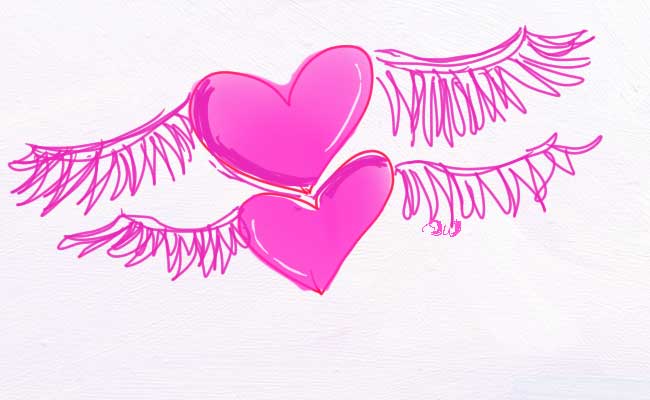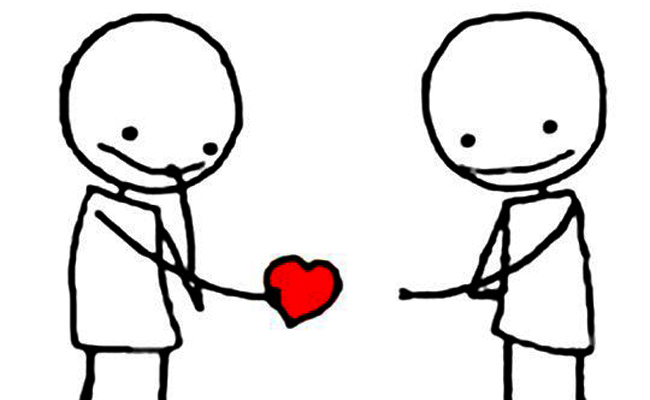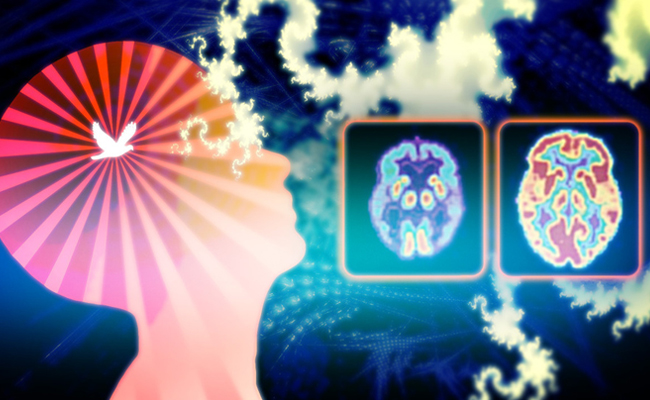Warna asli cat pintu kamar itu sudah tidak terlihat. Warna yang sekarang terlihat adalah krem, cenderung coklat dengan banyak bercak-bercak hitam. Begitu pintu kamar dibuka, aroma pesing dan bau kotoran manusia menyengat hidung. Aku mundur selangkah dan menutupi hidungku dengan sapu tangan. Di sudut ruangan, seorang cewek kurus duduk di lantai. Tatapan matanya kosong. Aku memandangnya dengan penuh rasa iba. Air mataku mengalir deras.
“Shanti…,” aku coba menyapanya. Sejenak hening. “Shanti…,” aku ulangi sekali lagi, dengan suara lebih keras. Kepala teman masa kecilku itu menatap ke arahku, masih tanpa ekspresi.
“Shanti, kamu masih ingat aku,” kataku. “Aku Winda, teman mainmu saat SD. Masih ingat nggak? Ini, ada Sisi. Kita dulu sering main petak umpet bertiga, pergi sekolah bersama,” ceritaku. “Kita pernah ke studio foto dan foto bertiga. Ini fotonya,” aku berusaha agar Shanti mengingat kami, aku dan Sisi.
Dalam sorot mata Shanti, aku melihat secercah kegembiraan. Tampaknya ia mulai mengingat kami. Sisi masih tetap berdiri di belakangku, diam tanpa suara.
“Tante tinggal dulu ya? Tante lihat kondisi Shanti baik, tatapan matanya tidak kosong ataupun penuh kemarahan,” kata Tante Ema.
Hari itu, aku merasa gembira. Aku mampu membuat Shanti, teman main masa kecilku tersenyum, meski kami tidak bisa berkomunikasi. Aku dan Sisi memandikan Shanti, memakaikan baju layak pakai, mengajaknya ngobrol, meski sebenarnya Shanti hanya diam ketika aku dan Sisi terus-menerus menceritakan masa kecil kami bertiga. Aku gembira karena ekspresinya lebih tenang dan tatapan matanya tidak kosong.
Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus. Aku harus kembali ke Palembang, kembali ke rutinitas harianku, bekerja. Aku kembali ke kota ini karena cerita Sisi lewat WA:
Winda, kamu balik dong. Minta cuti atau setidaknya Sabtu Minggu kamu ke sini. Kita janjian. Aku juga akan ke Bekasi. Kita ke rumah Shanti, teman main kita waktu kecil. Kondisinya makin parah. Ia sering mengamuk, kata Tante Ema, Shanti sering membentur-benturkan kepalanya ke pintu, berteriak keras, dan menangis.
Aku juga baru tau keadaan Shanti baru-baru ini dari Nina, sepupuku. Nina menceritakan semua kepadaku. Kita bertiga terpisah kota sejak tamat SD. Kita hanya dengar sedikit kisah tentang Shanti. Semula aku hanya dapat kabar Shanti berhenti sekolah. Ia hanya sekolah beberapa bulan di kelas 1 SMP. Ia sering melamun di kelas dan sering senyum-senyum sendiri. Akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah.
Tante Ema, yang kita tau adalah mama Shanti, ternyata bukan mama kandungnya. Kalau Shanti melakukan kesalahan, Tante Ema sering berteriak, “Pulang lu ke rumah Deti. Itu mama kandung lu.” Kalimat ini terus-menerus diucapkan saat Tante Ema marah.
Shanti memendam sendiri semua perkataan dan perlakuan kasar Tante Ema. Karena tidak kuat, ia mengalami goncangan jiwa.
Semula hanya senyum-senyum sendiri, kemudian berteriak keras, membenturkan kepalanya ke pintu atau tembok, dan mengamuk.
* * * * *
Aku memandangi foto kami bertiga, aku, Shanti, dan Sisi. Foto jadul yang warnanya sudah mulai pudar. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku tak menyangka, itu satu-satunya foto kenangan kami bertiga. Waktu itu, setelah pembagian raport, kami bertiga bermain seperti biasanya. Aku mengusulkan agar kami ke studio foto untuk berfoto bersama. Shanti dan Sisi setuju.
Shanti, gadis cantik yang malang. Wajahnya cantik, nilai sekolahnya pun terbilang baik. Shanti selalu masuk 10 besar di kelas. Sayang “nasibnya” tidak seindah wajahnya.
Aku baru tau, masalahnya dimulai sejak kelas 6 SD. Aku dulu merasa heran, mengapa anak sepintar Shanti lulus SD hanya dengan NEM* rata-rata hanya tiga koma sekian. Lulus SD, keluargaku pindah ke Palembang, keluarga Sisi pindah ke Makassar. Sementara keluarga Shanti tetap tinggal di Bekasi, kota kelahiranku.
Kami, aku dan Sisi masih sering berkomunikasi, sementara dengan Shanti, komunikasi kami putus total. Kami pun disibukkan dengan kegiatan masing-masing.
Ajakan Sisi akhirnya terwujud dan kami bertiga bisa “reuni”. Kami “ngobrol” dan memandikan Shanti. Aku sangat gembira dengan perkembangan hari itu. Seharian kami bersama. Aku dan Sisi mengajak Shanti menelusuri tempat kenangan saat dulu kami kecil.
Baca juga: Pelangi di Dalam Hati
Saat kami bersama, Shanti tidak seperti mayat hidup, istilah Tante Ema karena Shanti bisa diam dan tak melakukan aktivitas apa pun seharian. Hanya duduk atau berbaring saja, hanya napas yang menandakan bahwa Shanti masih hidup.
Memang Shanti tidak berinteraksi, tapi kami merasakan Shanti berbahagia bersama kami. Tante Ema pun menyebut kami dukun sakti. Kami mampu menjinakkan Shanti, mengajaknya jalan tanpa menimbulkan kekacauan. Bahkan saat kami mampir ke rumah Nina, kami duduk di teras rumah, Shanti merebahkan kepalanya di bahuku.
Waktu jua yang harus memisahkan kami. Kami harus kembali ke kota kami, kembali ke rutinitas kami.
Hari ini aku mendapat kabar duka. “Winda, tadi pagi Shanti meninggal dunia. Shanti ditemukan tewas tergantung dengan celana panjang di kamarnya,” begitu bunyi WA Sisi.
Semua kerjaan kantor kutinggalkan. Aku minta izin pada bos, lalu aku terbang ke Jakarta. Sisi juga ke Jakarta. Nina menjemput kami di Bandara Soekarno-Hatta.
Pemakaman Shanti sudah selesai. Kini kami tinggal berdua, aku dan Sisi di kamar di rumah Nina. Kami berdua masih tak percaya, secepat itu Shanti pergi dan dengan cara yang tragis. Mata kami sembap karena terus-menerus menangis.
Kami berdua berbaring di kasur, menatap kosong ke langit-langit kamar. Kami tidak bicara, pikiranku mengembara ke masa lalu, saat kami menikmati masa kecil yang indah, bermain bersama-sama. Mungkin pikiran Sisi pun sama, mengembara ke masa lalu. Aku ingat, Buddha selalu mengajarkan agar kita menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ucapan kasar Tante Ema telah menghancurkan hati sahabatku, dan kami harus kehilangan sahabat. “Selamat jalan Shanti, semoga kau terlahir di alam bahagia…”
*Nilai Ebtanas Murni.
Catatan:
Cerpen ini terinspirasi dari kisah nyata kiriman seorang teman, tentu dengan sedikit bumbu. Semua nama telah penulis ganti. Buat Anda yang kebetulan telah menikah dan tidak dikaruniai anak, sebaiknya Anda tidak mengadopsi anak jika tidak yakin mampu mencurahkan kasih sayang, merawatnya dengan baik, dan tidak melukai perasaannya dengan mengatakan ia bukan anak kandung, apalagi mengusirnya. Semoga kisah nyata ini tidak terulang kembali.

Suami Linda Muditavati, ayah 2 putra dari Anathapindika Dravichi Jan dan Revata Dracozwei Jan.Pembuat apps Buddhapedia, suka sulap dan menulis, tinggal di Bandung.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara