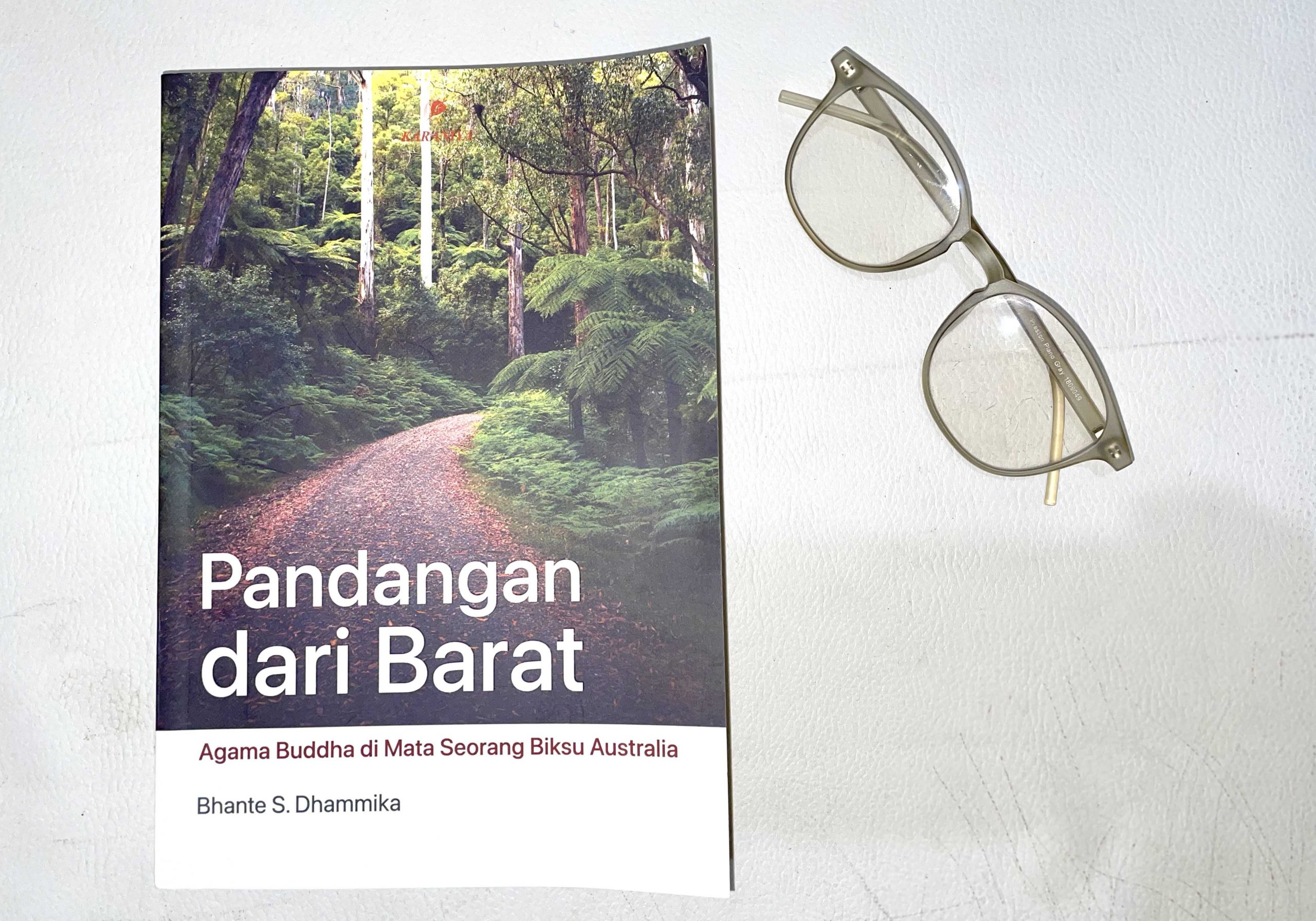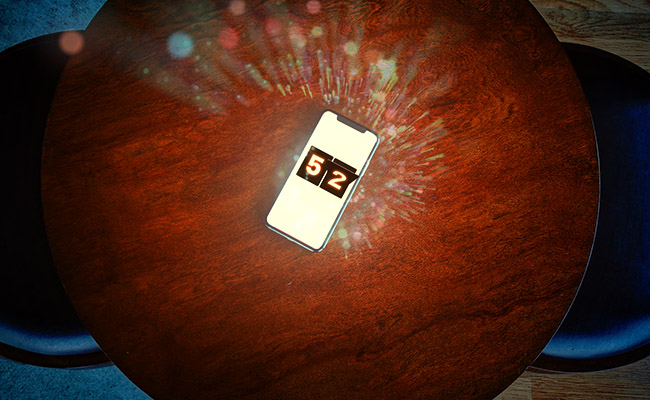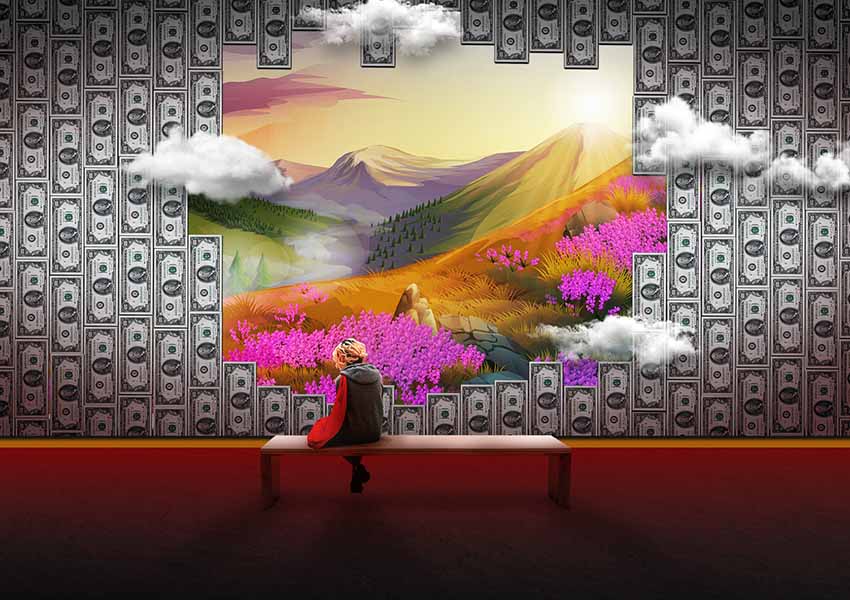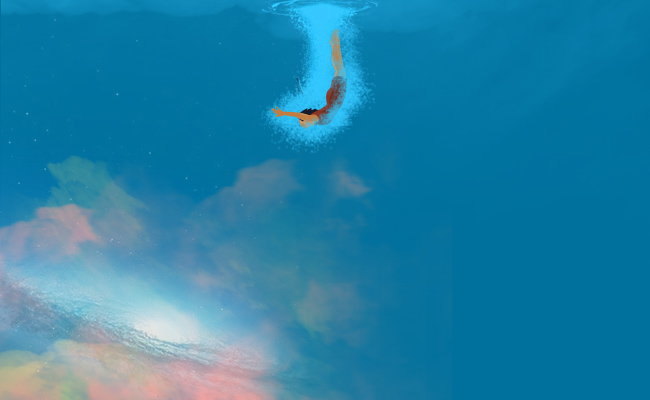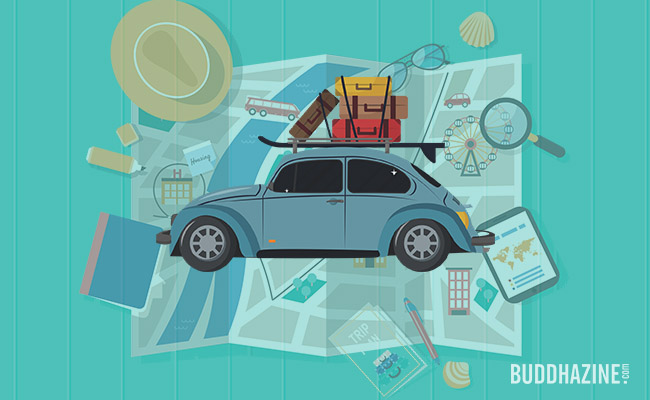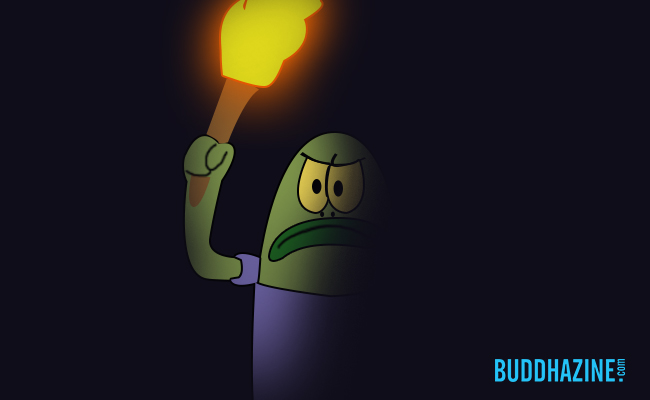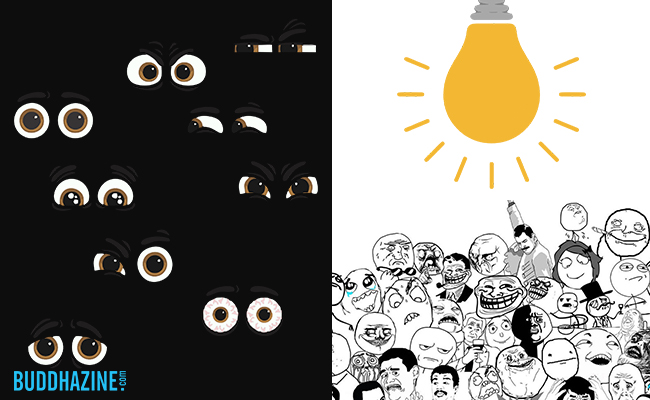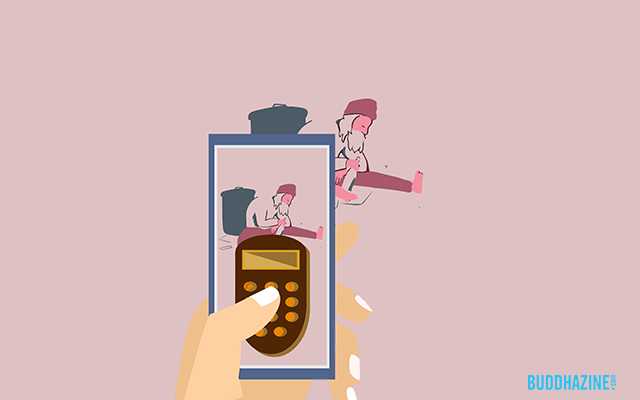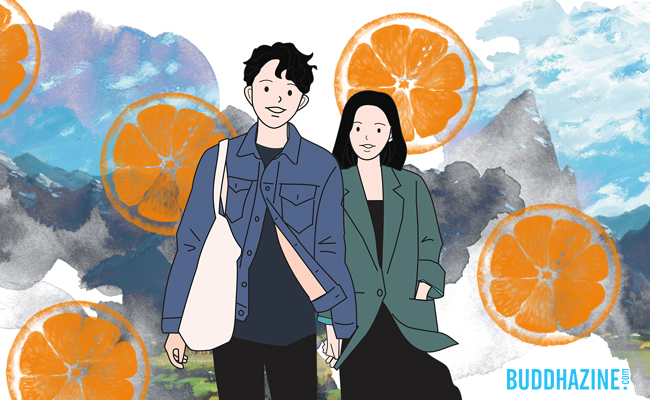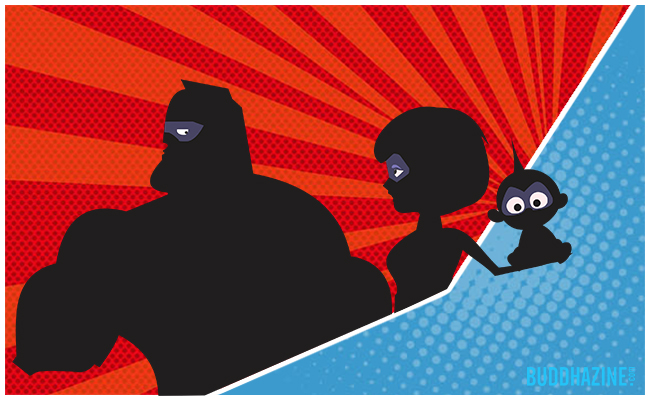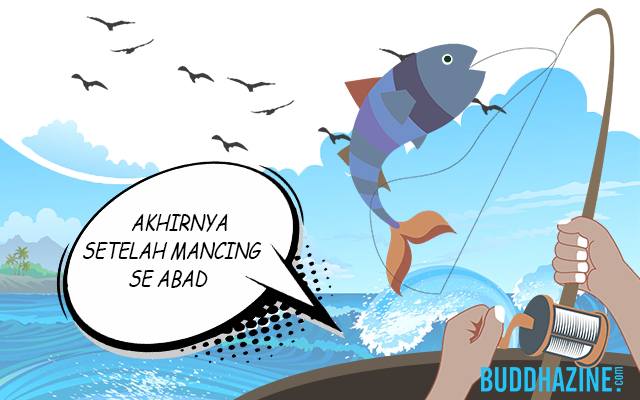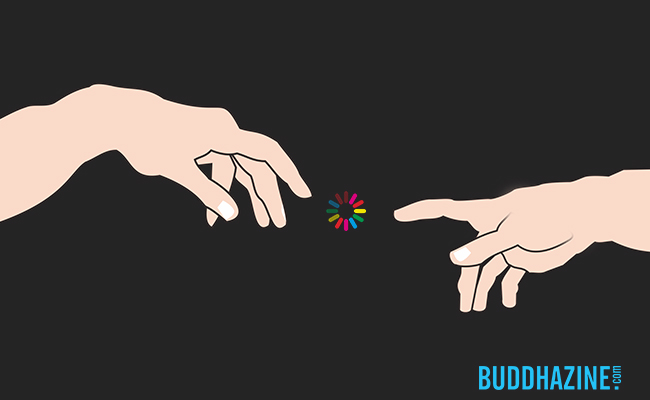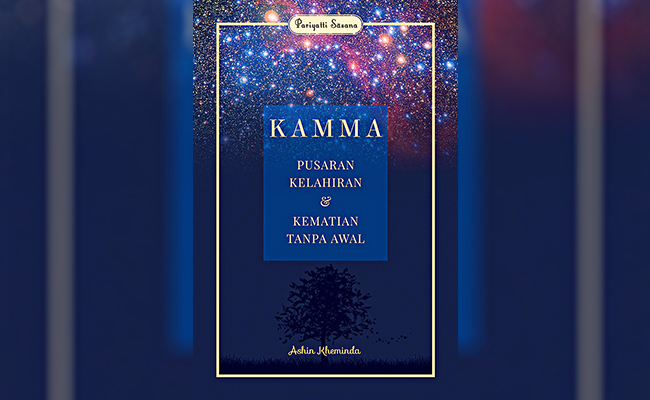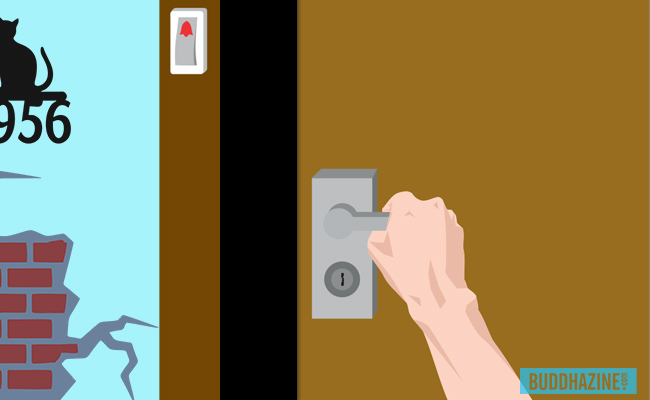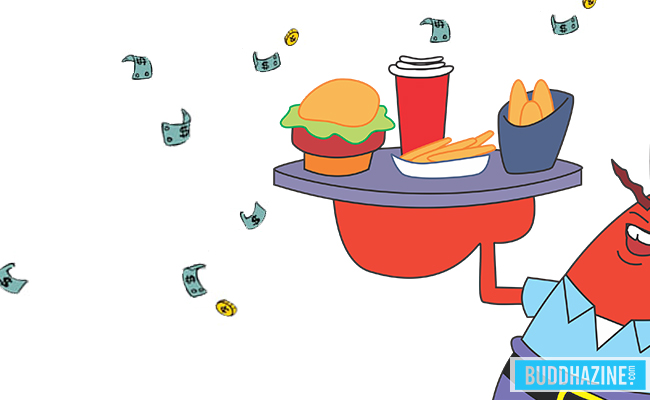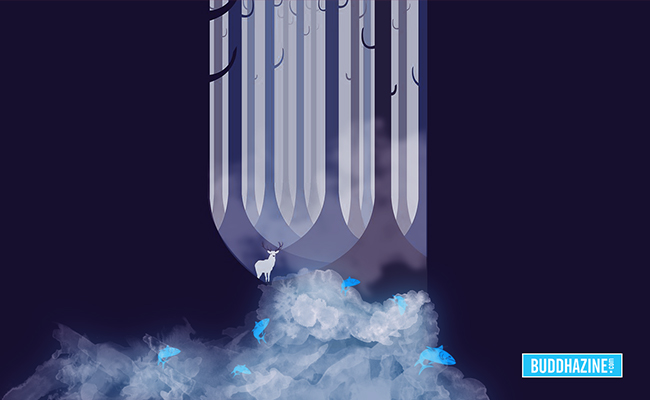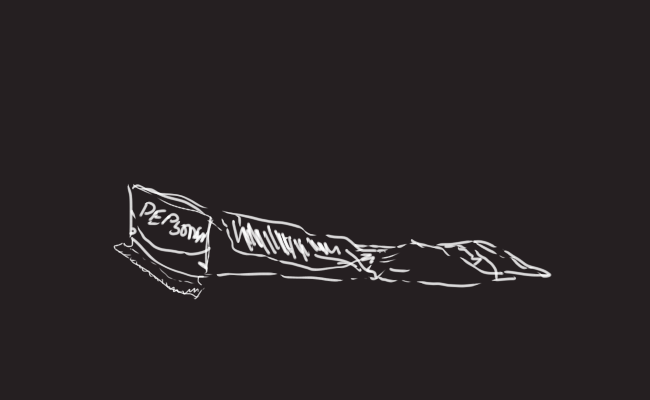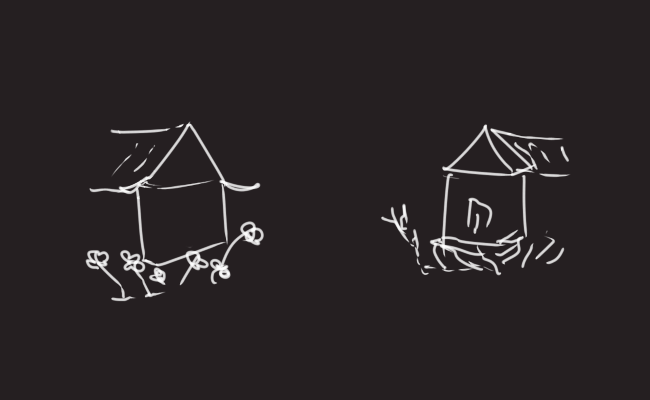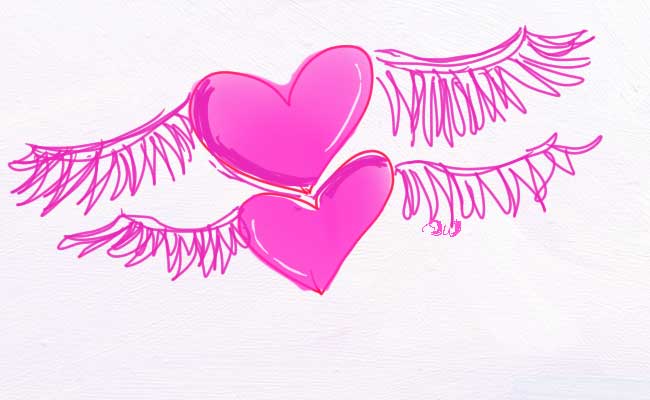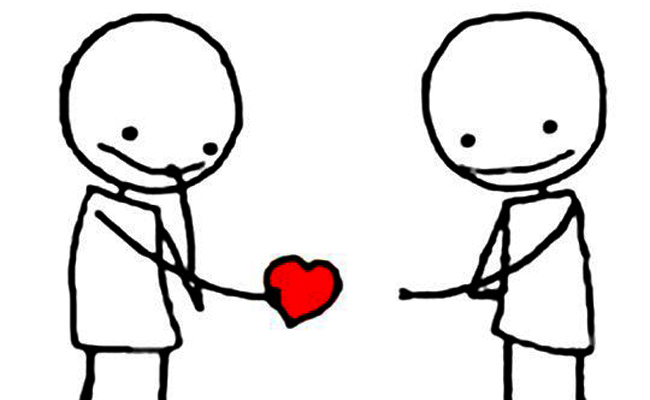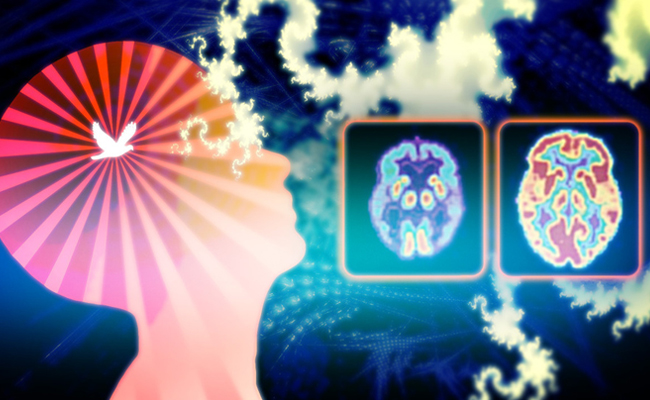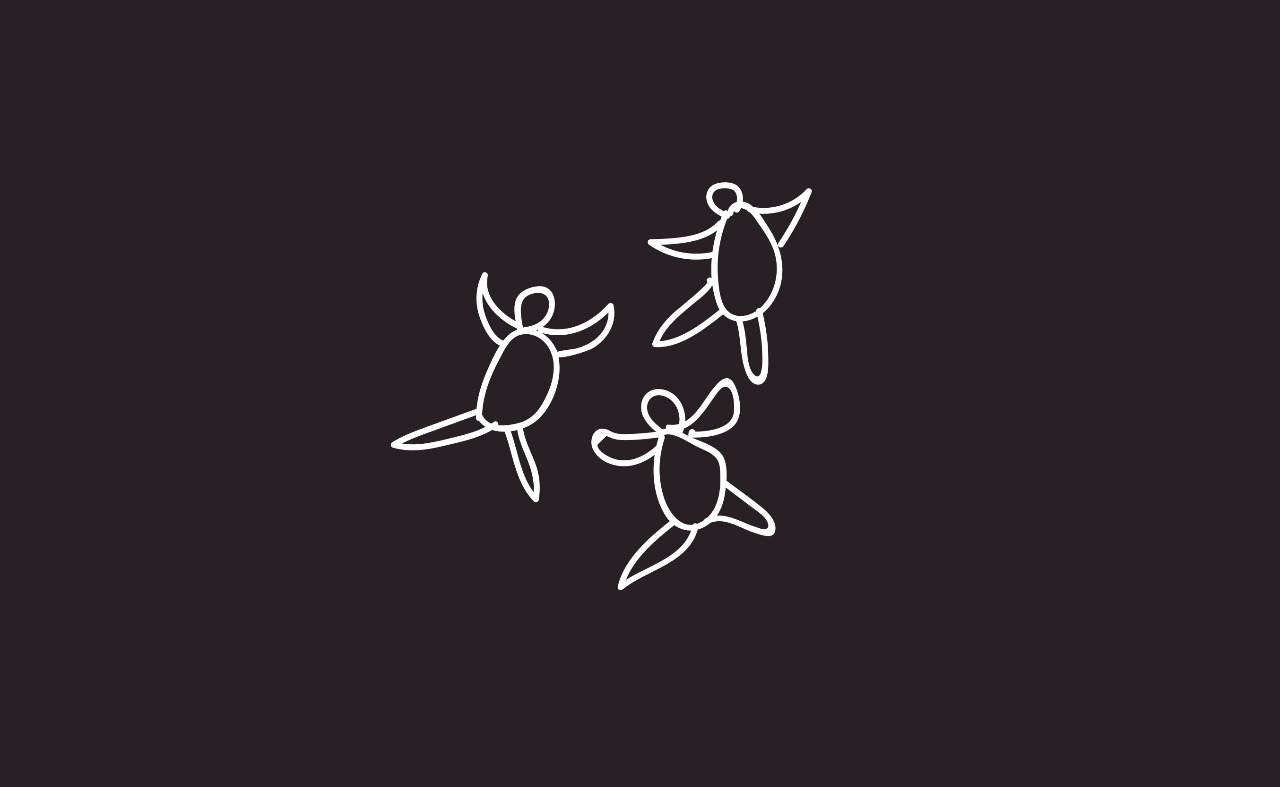
Bumi akan mengalami pergantian napas yang mendiami. Tinggal bagaimana kita; menjadi temaram surut atau teladan di kemudian hari~Wira Nagara
Betapa indahnya cuaca hari ini. Langit biru, awan putih yang bergerak di langit, matahari cerah. Tepat hari Minggu, jam tujuh pagi. Tepat untuk bergembira ria, tepat untuk bersenang-senang, menonton televisi, mendengarkan musik, baca buku, tepat untuk segala-galanya.
Aku bangun pukul setengah enam. Walau weker sudah diatur jam lima pagi. Aku mengenakan piyama warna oranye berharap masih bisa menikmati waktu tidur setengah jam lagi. Terlalu dingin untuk menyentuh air di pagi hari.
Hari libur.
Libur telah tiba. Setelah rutinitas kerja dilalui setiap harinya. Waktunya untuk ‘me-time’. Ternyata keadaannya berbeda, aku harus melakukan kegiatan rutin lainnya yaitu pergi ke vihara, ke sekolah Minggu. Hah! Masih sekolah Minggu? Iya, masih ngajar sekolah Minggu.
Aku menghela napas dalam-dalam, bergumam dalam hati mengapa aku berbeda dengan yang lainnya? Yang bisa menikmati waktu dengan bebas. Satu jam berlalu dengan cepat, aku mengembangkan senyumku, mengenakan celana jeans dan kemeja kotak-kotak warna pink.
“Selamat pagi, Namo Buddhaya,” ucapku begitu kaki melangkah memasuki vihara.
“Namo Buddhaya, Kak,” adik-adik menjawab sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Pemandangan yang menakjubkan. Senyum dari anak-anak mungil dan celotehan-celotehan lucu lainnya. Aku namaskara di depan altar dan menata buku Paritta. Detik jam berjalan stabil. Lantunan Paritta suci mulai dikumandangkan, kadang dengan lantang, suara melemah, lantang kembali, dan seketika hening lalu dengan nada tinggi. Intonasi suara yang tidak stabil, segera aku mengontrol supaya bisa senada pengucapannya.
Setelah selesai meditasi, tanpa sengaja aku menoleh pada anak kecil yang duduk paling belakang. Murid baru. Tangannya memegang erat wanita yang di sampingnya, sesekali berbisik, entah apakah saling mendengar. Mereka berdua terlihat seperti manusia yang bingung. Lagi asyik-asyiknya dengan pemandangan yang kunikmati sendiri, seseorang menepuk-nepuk tanganku.
“Kak, kita mau ngapain?” kata bocah laki-laki yang berlesung pipit, umurnya baru tiga tahun dan namanya Leon.
“Ah, iya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita,” balasku sambil tersenyum.
Sebelum cerita dimulai, aku memanggil anak yang duduk paling belakang untuk maju dan memperkenalkan diri. Kebiasaan kalau ada anak baru harus dikenalkan supaya lebih akrab dengan anak-anak lain. Anak itu masih celingak-celinguk, kaku dan menarik tangan wanita di sebelahnya.
“Tidak apa-apa Ci, ikut saja,” pintaku.
Wanita itu berkaca-kaca dan meminta maaf sambil memeluk bocah lelaki yang terlihat banyak luka di sekujur tubuhnya. Bukan luka siksaan tapi seperti luka akibat garukan tangan, seperti rasa gatal yang tak berkesudahan. Semua mata terbelalak ke arah mereka berdua, dan suasana menjadi mencekam karena rasa sedih. Terharu dan tanpa kata-kata namun sudah menusuk dasar hati terdalam.
“Oke, namaku Kak Helen. Adik ini siapa namanya?” ucapku mencairkan suasana.
“Nama aku Aldi, dan ini Mamaku,” jawab bocah itu sambil tersenyum, suaranya lantang dan matanya seketika berbinar.
“Umur aku 6 tahun, hobi aku membaca tapi aku tidak boleh sekolah. Aku ingin belajar dan bermain bersama teman-teman,” lanjut Aldi.
“Tapi aku nurut sama Mama aja,” Aldi nyengir. Senyuman Aldi membuat mamanya tidak bisa menahan air mata dan sesenggukan. Ada kisah yang pilu yang masih belum terungkap.
“Wah keren Aldi. Adik-adik bilang halo dan selamat datang dong,” pintaku. Tidak butuh waktu lama untuk mereka saling akrab, meski ada beberapa anak yang tidak mau dekat-dekat karena takut penampilan Aldi, tapi mamanya sudah berbisik kepadaku bahwa itu bukanlah penyakit yang menular. Aku berjuang keras agar mataku tidak dipenuhi dengan air. Aku mulai bercerita kisah jataka, kehidupan lampau Buddha ketika menjadi seekor kelinci yang diuji oleh Dewa Saka. Semua mendengarkan dengan saksama, kadang kala ada yang rela menjadi seekor kelinci melompat-lompat. Semua tertawa dan tertawa itu melegakan.
Selesai kebaktian, Mama Aldi menghampiriku dan mengucapkan terima kasih.
“Maaf Ci, Aldi sakit apa ya?” tanyaku.
“Saya juga tidak tahu, sudah dibawa berobat ke mana-mana tapi penyakitnya tidak diketahui, saya juga merasa kasihan sama Aldi,” jawab Mama Aldi.
“Yang sabar ya Ci, semoga segala penyakit yang diderita Aldi segera hilang,” imbuhku.
“Iya Helen, terima kasih. Mungkin ini karma yang harus diterima, dan terima kasih juga sudah diterima dengan baik di sini, sebenarnya saya cuma mampir tapi Aldi sangat senang. Setelah ini kami akan kembali ke Jakarta,” Mama Aldi menghembuskan napasnya dalam.
“Sama-sama Cici, jangan sungkan ya, kalau ada waktu datang lagi kemari,” jawabku. Setelah itu Aldi beserta keluarganya pamit pulang.
Karma? Aku tersentak. Ya, setiap orang memiliki akibat dari perbuatannya sendiri, tapi sungguh pilu rasanya melihat anak sekecil itu menanggung beban yang berat seperti itu, dan setiap orang memang berbeda. Kenapa? Aku memejamkan mata, tanyakan padaku apa yang aku inginkan. Karena hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan.

Penulis cerpen, guru sekolah Minggu di sebuah vihara, menyukai dunia anak-anak.
Hobi membaca, jalan-jalan, dan makan.