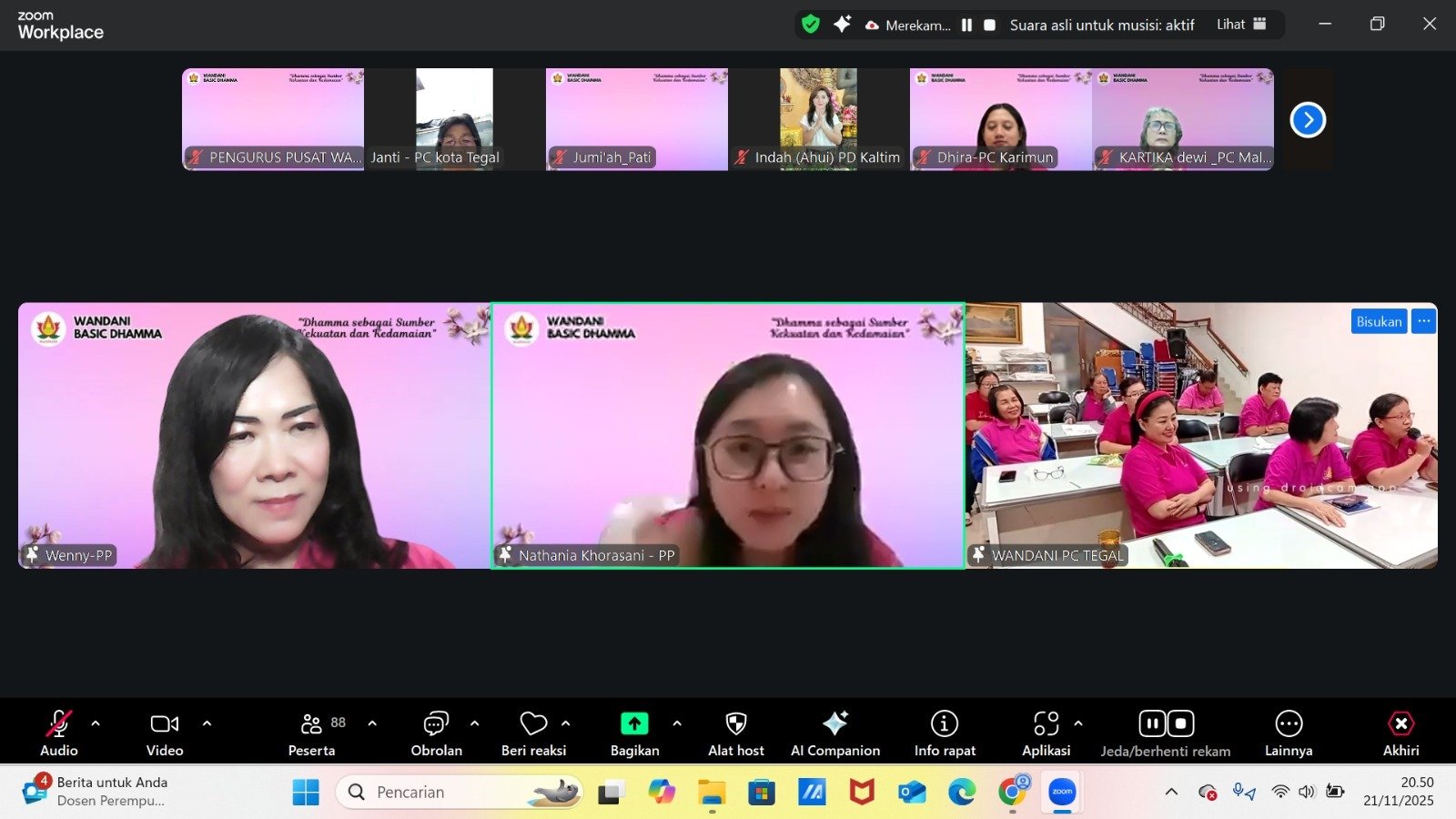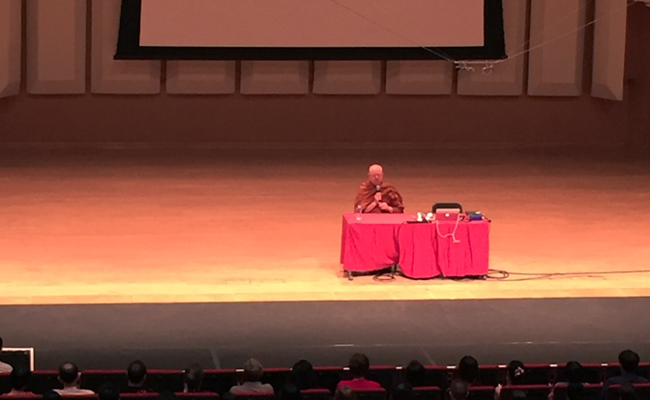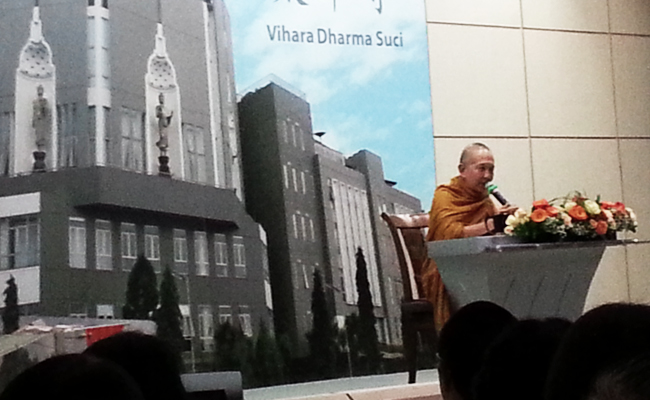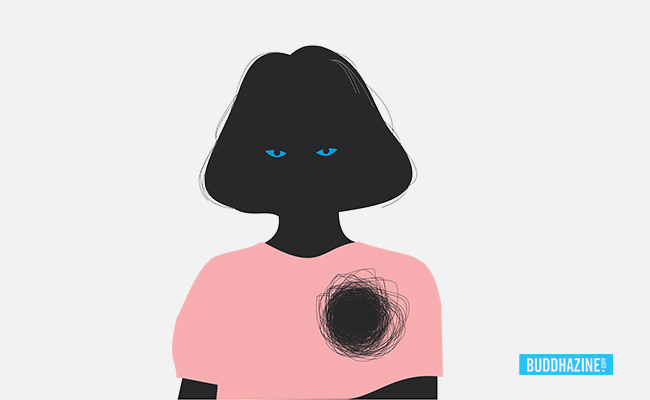
Pernahkah kita berpikir bahwa dalam mempelajari Dharma, kita justru tidak beranjak dari apa pun. Perilaku kita mungkin nampak “Buddhis”, namun dalam banyak hal Dharma yang kita pahami itu hanya menjadi dasar pembenaran atas apa yang sudah ada atau kita lakukan sebelumnya. Dengan dalih kecocokan pandangan hidup, pilihan atas pencarian Dharma, bahkan jodoh Dharma, namun itu semua hanya pilihan Dharma dalam keterkondisian.
Kita mulai memahami hal ini dari sebuah kata Sanskerta “avidya”. Kata ini diterjemahkan menjadi ignorance. Arti yang paling sering digunakan adalah ketidaktahuan. Namun hal ini bukan sekedar ketidaktahuan, tapi juga keengganan untuk mengetahui. Secara praktis adalah ketidakpedulian dan ketidakpekaan. Bukan hanya seputar diri sendiri tapi juga orang lain, bahkan urusan sosial kemasyarakatan.
Ketidakpedulian turut menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Akibat ketidakpedulian seperti yang pernah diungkapkan oleh Albert Einstein, “Dunia tidak akan hancur oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang hanya melihat tanpa melakukan apa pun.”
Kita akan melihat diskursus tentang avidya ini di Barat sebelum melihatnya di Indonesia. Bhikkhu Bodhi, seorang bhikkhu Theravada Amerika menegaskan, “Di dunia sekarang ini, tidak cukup hanya untuk puas dengan mengembangkan cinta kasih dan welas asih sebagai kualitas batin, kita juga harus mampu mengubah keadaan batin ini menjadi tindakan praktis yang membawa bantuan nyata untuk penderitaan makhluk hidup lainnya.”
Pandangan Bhikkhu Bodhi seperti ini bukan hal baru. Belajar dari sejarah agama Buddha, cikal bakal Buddhis Mahayana juga didorong oleh semangat kepedulian pada penderitaan makhluk lain. Pada akhir abad ke-20, digunakan istilah “Engaged Buddhism” sebagai upaya para praktisi Buddhis dalam mengembangkan praktik yang menyesuaikan realitas sosial dan ekologi zaman ini.
Regina Valdez, seorang anggota dari New York Insight and Buddhist Global Relief, pernah bertanya pada Bhikkhu Bodhi dalam suatu wawancara. “Bhante, Anda seorang sarjana dan penerjemah Buddhis. Apa yang menarik Anda ke gerakan Engaged Buddhism?”
Bhikkhu Bodhi menjawab, “Sebelum menjadi seorang biarawan, saya aktif dalam gerakan anti-perang selama Vietnam dan menjadi pembela nilai-nilai dan cita-cita sosial yang progresif. Sebagai seorang bhikkhu, saya mengundurkan diri untuk fokus pada pengembangan spiritual pribadi saya. Tetapi lama kelamaan saya merasa bahwa visi saya tentang kehidupan spiritual telah menjadi sangat sempit. Saya menyadari bahwa perkembangan moral dan spiritual yang lebih integral harus mencakup baik kultivasi ketenangan batin dan komitmen untuk membantu mereka yang menderita oleh penderitaan akibat kemiskinan, perang, rasisme, dan ketidakadilan sosial. Saya merasa bahwa sebagai seorang Buddhis saya harus meletakkan nilai-nilai cinta kasih dan welas asih ke dalam tindakan dengan cara-cara yang akan mengatasi bentuk penderitaan yang keras dan merendahkan yang orang-orang terpapar hari ini. Seiring waktu, ini mengarah pada penciptaan Bantuan Global Buddha.”
Baca juga: Buddhadharma dan Kehendak Gen
Pilihan Dharma dalam keterkondisian bisa berlaku pada siapa saja. Seperti Bhikkhu Bodhi yang pada awalnya terkondisi pada praktik eksklusif walaupun pada waktu beliau masih sebagai umat awam juga seorang aktivis anti perang Vietnam.
Kita bisa melihat fenomena perkembangam agama Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah Pilihan Dharma yang pada awalnya lebih didorong pada pencarian identitas budaya. Kerinduan untuk memahami kejayaan agama Buddha pada zaman Sriwijaya dan Majapahit.
Fenomena yang lain adalah pencarian rasional yang lebih karena kecocokan cara berpikir, terlepas ada bias keterkondisian minoritas yang menyertakan “ketidakpedulian” dengan urusan sosial politik.
Dari dua fenomena ini saja, kita menjadi tidak heran jika kecenderungan umat Buddha yang eksklusif, hanya bergerak dan memikirkan kelompok minoritasnya saja. Ditambah lagi kepentingan sekte dalam agama Buddha membuatnya semakin menjadi “double minority”.
Ketika zaman reformasi, pelan namun pasti, zaman sudah berubah. Minoritas mulai mendapat ruang publik yang lebih baik, terlepas proses berdemokrasi seperti inipun tidak selalu mulus dan belum ideal. Namun harus disadari perubahan seperti itu sudah terjadi.
Agama Buddha di tanah air saat ini sedang beradaptasi dengan kondisi baru ini. Ketidakpedulian akan masalah sosial politik menjadi kian terlihat. Persis yang dialami Bhikkhu Bodhi yang pada akhirnya menyadari visi pengembangan spiritualnya yang sempit. Perubahan visi selalu terjadi setelah adanya penyadaran. Bagian terpentingnya, kita mesti memahami bahwa upaya penyadaran seperti ini selaras dengan praktik.
Suatu penyadaran itu memang tidak mudah, selain mesti muncul dari dalam, juga semua itu membutuhkan proses.
Jika di Barat ada “Engaged Buddhism“, lalu bagaimana untuk yang di Indonesia? Wujud praktik Engaged Buddhism dalam konteks Indonesia tentu tidak harus sama persis seperti yang ada di Barat. Atau kita agama Buddha saat ini belum siap, jadinya tentu lebih mudah sekadar “copy-paste” dari apa yang ada di Barat.
Semua ini pilihan Dharma dalam keterkondisian.

Desainer batik tulis. Tinggal di Kudus, Jawa Tengah.