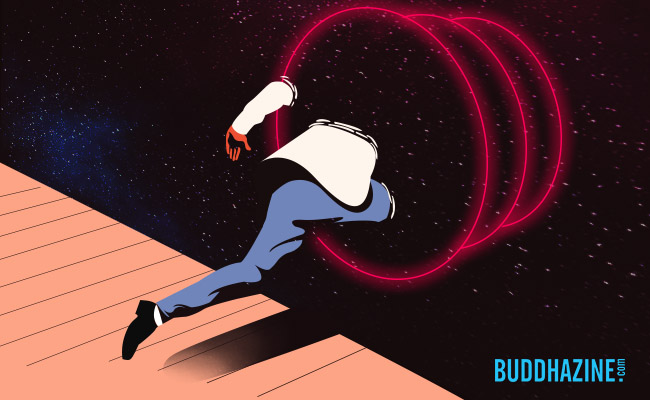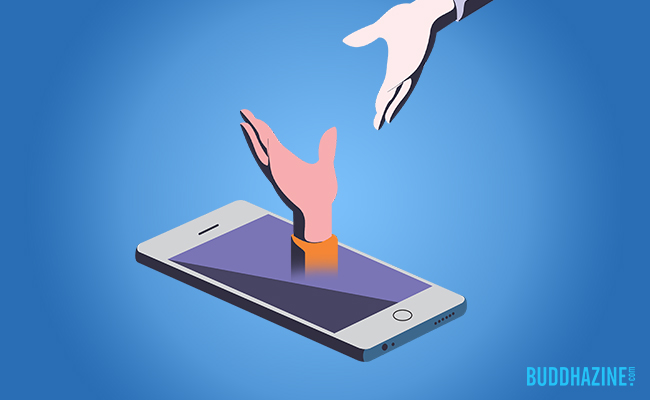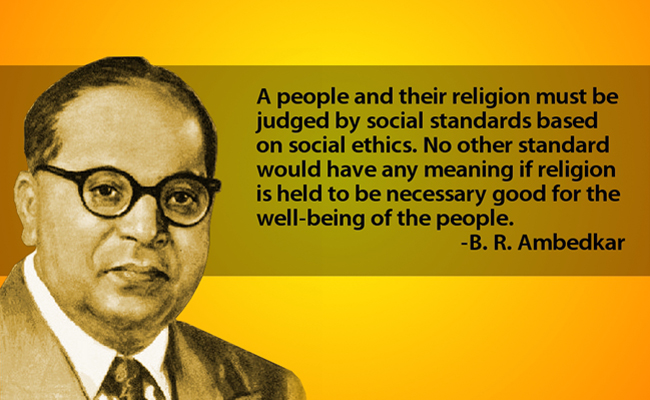Penulis : Andreian (An)
Sebuah mini bus tua berjalan gontai membawa belasan manusia. Suasana jalan yang mulai ramai membuat laju bus menjadi lambat. Adi yang sedari tadi berdiri di sisi belakang terlihat semakin cemas. Bukan, bukan karena aroma keringat atau kepulan asap rokok yang membuatnya tidak nyaman. Kenyataan bahwa senja semakin kehilangan berkas cahaya membuat pikirannya sudah sampai di rumah sekalipun raganya masih terjebak dalam perjalanan. Adi memang selalu terburu-buru setiap pulang kerja, sebab ia takut nasi di dalam tasnya sudah kehilangan hawa panas atau yang di rumah sedang menunggu telah terbaring dengan harapan yang terhempas.
Bus tiba-tiba berhenti. Wajah-wajah mengantuk terlihat kebingungan memandang ke berbagai arah. Adi yang sedari tadi melihat keluar jendela bersikap cukup datar. Ia tahu ada penumpang turun, seorang wanita tua dengan jarit dan baju tradisional jawa yang sudah lusuh. Melihat wanita itu menggendong keranjang bambu berisi botol-botol jamu entah mengapa membuat Adi semakin gelisah. Terlebih ketika bus kembali berjalan dan perhatiannya beralih pada seorang kakek tua yang tengah duduk sembari memakan sepotong gorengan di sebelahnya. Kakek itu terlihat menikmati makanannya, mulai dari cara menggigit, mengunyah, hingga ketika menelan perlahan-lahan.
“Kau mau Nak?” Kakek itu menawarkan gorengan menyadari Adi terus memperhatikannya.
“Ti- dak! Terima kasih, Kek. Saya sudah hampir sampai,” jawab Adi kikuk.
Kakek itu tersenyum, sedangkan Adi menundukkan kepala sebelum bergerak maju menembus kerumunan. Di depan pintu Ia segera memberikan kode pada kenek, lalu dengan satu loncatan turun di tepi jalan yang sepi. Adi terlihat sedikit tergesa-gesa ketika melanjutka perjalanan menyusuri gang menuju rumahnya. Langkah yang panjang dan cepat membuat napas tersengal-sengal, wajahnya pun jadi pucat dengan kesan kepanikan yang dalam. Bila delik waktu di tari ke masa lalu, ekspresi wajah Adi sama seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu.
Kala itu Adi juga pulang terlambat. Ia berlari tergesa-gesa karena kegelisahannya sepanjang hari terjawab dengan kabar buruk dari rumah. Kabar itu memang tidak terlalu jelas pada mulanya, sebab mbok Tun terlalu panik untuk dapat berbicara dengan baik melalui telepon. Namun tetangga Adi itu juga yang pada akhirnya melengkapi potongan informasi membingungkan menjadi sebuah kenyataan memilukan.
“Ealah, Adi!” Mbok Tun memekik melihat Adi berlari dari kejauhan. Adi tidak menjawab, ia terus berlari demi mendengar apa yang akan disampaikan Mbok Tun dengan lebih jelas.
“Bapakmu jatuh, Di.” Mbok Tun berusaha menerangkan kembali ketika Adi sudah sampai di depannya. “Dia tergelincir lalu jatuh dari pohon kelapa. Sekarang sedang di rawat di rumah sakit kecamatan.”
“Terima kasih Mbok, kabarnya.” Adi kembali berlari, kali ini menuju jalan raya. Sampai di sana ia melihat ke arah barat, jalanan padat kendaraan, tetapi tidak ada satu pun angkot. Suasana semakin panik karena malam datang lebih cepat.
“Aku tidak bisa menunggu!” Adi memekik dalam hati dan mulai berlari. Kali ini ia menuju sebuah pangkalan ojek. Sedikit jauh, tetapi itu pilihan yang baik. Menunggu angkot butuh waktu, jika sudah dapat masih terjebak macet juga.
“Mas, antar saya ke rumah sakit sekarang.” kata Adi pada salah seorang tukang ojek.
“Baik, Mas.” jawab tukang ojek dengan sigap.
Motor segera melaju membawa Adi dan kegelisahannya. Di perjalanan ia terus memikirkan bapaknya. Lelaki tua yang sangat ia sayangi itu seharusnya tidak perlu memanjat kelapa lagi. Adi sendiri sudah melarangnya berkali-kali karena khawatir akan terjadi hal seperti ini. Namun naluri seorang ayah berkata lain. Mbah Tomo masih bersikeras ingin bekerja sekalipun puteranya sudah berniat menyokong semua kebutuhan kelurga.
“Pensiunlah, Pak. Kau bisa istirahat atau mengambil pekerjaan lain yang lebih aman.” kata Adi pada suatu malam.
“Aku senang dengan pekerjaan ini, menganggur akan membuatku tidak enak badan.” jawab mbah Tomo sembari berkelakar.
—
Adi sedikit tercekat ketika motor tiba-tiba berhenti. “Sudah sampai Mas.”
“Oh, terima kasih Mas.” Adi bergegas setelah membayar ongkos.
Lorong rumah sakit terlihat sangat bersih, bau antiseptik memenuhi udara, dan lantai yang berhias keramik putih membuat suhu terasa dingin. Adi sampai di depan sebuah ruangan, masih dengan perasaan yang berkecamuk ia menemukan ibunya tengah duduk di bangku tunggu. Wanita itu memang sudah tua, dia lebih cocok duduk di ruang tamu atau sekedar menunggu nyala api di depan tungku alih-alih menangis di depan ruang gawat darurat.
“Bu …” Adi duduk dan memeluk ibunya. Sesaat hanya suara isak tangis yang menggema dalam lorong itu.Peluk dan tangis mungkin menjadi bahasa yang paling sederhana untuk saling bertukar rasa antara ibu dan anak yang tengah dirundung gulana itu.
“Bapakmu lumpuh, Nak.” Parau, suara ibu terdengar memilukan setelah lama tertahan oleh isak tangis. Adi tidak menjawab, ia mengelus pundak ibunya demi menyalurkan empati dan ketenangan ….
Hari ini Adi seolah mengulang momen yang sama, pulang terlambat, firasat buruk, berlari tergesa, napas sesak, senja yang menghitam, jalanan sepi. “Ah, aku harus segera sampai!” kata Adi sembari mempercepat langkah.
Sampai di depan rumah Adi berhenti sembari memegang lutut. Saat itu pintu rumah sedikit terbuka, sorot lampu memijar keluar menciptakan berkas cahaya temaram. Dari luar, terdengar suara lelaki tengah berbicara.
“Ini sudah tiga bulan, kontrakan harus segera dibayar, Bu!” kata lelaki itu.
“Maaf, Pak, jika boleh saya minta kelonggaran lagi. Kami bukan mau berkelit dan tidak bersedia membayar, tetapi kondisi memang sedang buruk. Sebelum ini kami juga selalu menunaikan kewajiban tepat pada waktunya.”
“Kami paham dengan apa yang sedang kalian alami, Bu, tapi kami punya tanggung jawab untuk melakukan tugas ini. Sebisa mungkin akan kami usahakan apa yang Ibu harapkan. Namun jika minggu-minggu ini pak Suro datang atau mengutus kami menangih lagi, itu sudah di luar kuasa kami.”
“Baik Pak, saya sangat berterimakasih atas bantuan ini, terima kasih, Pak.”
“Sama-sama, kami pulang sekarang.”
“Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih.”
Adi mundur dua langkah, beberapa detik kemudian dua lelaki berbadan besar keluar dari pintu rumah diikuti ibu. “Pak,” sapa Adi sembari tersenyum.
“Iya, Dek.” jawab dua lelaki itu.
“Terima kasih, Pak.” Adi berujar, dua lelaki itu tersenyum beberapa saat, mengangguk, laluu melangkah pergi ….
“Ayo Bu kita masuk.”
“Iya, Nak.” Mata Ibu terlihat berkaca-kaca.
Malam itu makan malam berlangsung hambar. Nasi bungkus yang Adi beli tidak mampu menyenangkan lidah siapapun kecuali mbah Tomo. Lelaki itu tidak tahu apa yang baru saja terjadi, Adi dan ibu juga sepakat untuk merahasiakannya. Barangkali keputusan itu kurang bijak, sebab ibu jadi begitu tertekan.
Hingga makan malam berlalu dan semua orang istirahat ibu masih terjaga. Ia begitu khawatir melihat kenyataan, semua tabungan sudah habis untuk berobat, pendapatannya sebagai pedagang sayur keliling sedang menurun, sementara gaji Adi tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Kegundahan itu semakin menjadi ketika bayangan pengusiran terus muncul di pikiran ibu. Membayangkan tidak punya rumah dengan kondisi suaminya yang tengah sakit membuat air matanya menetes sepanjang malam.
Puncak dari kegelisahan ibu adalah titik di mana tubuhnya tidak sanggup lagi menopang gejolak. Pada titik itu penyakit lamanya menyerang. Tepat ketika fajar datang dan wanita itu hendak ke kamar mandi, tubuhnya terpelanting jatuh karena tekanan darah tinggi tidak sanggup lagi dibendung. Adi yang mendengar suara berdentum segera berlari memastikan situasi. Ia sangat kaget ketika mendapati suara itu muncul dari lantai yang tertimpa badan ibunya. Beruntung kepala pusing tidak membuat ibu benar-benar kehilangan kesadaran, Adi juga sudah sangat paham bagaimana menghadapi situasi. Semenjak tahu darah tinggi dapat menyebabkan stroke, Adi mempelajari penyakit itu dengan mendalam. Meski demikian, butuh beberapa saat bagi Adi untuk memastikan keamanan ibunya hingga dapat kembali berbaring di ranjang. Di saat seperti itu keputusan memisahkan ranjang orang tuanya demi keamanan mbah Tomo ternyata bermanfaat, setidaknya lelaki tua itu tidak sampai terganggu. Namun meski kondisi sudah cukup kondusif, keadaan Ibu membuatnya tidak dapat beraktivitas, istirahat adalah hal terbaik alih-alih memaksakan diri dengan resiko keadaan yang semakin parah.
“Aku akan menyokong segala kebutuhan mereka,” tekad Adi sebelum keluar dari kamar itu dan memulai segala sesuatunya.
Adi memang benar-benar menyayangi kedua orang tuanya. Rasa bakti dan cinta membuatnya kehilangan rasa lelah untuk terus berusaha. Setidaknya dia harus mendapat uang untuk mengamankan tempat tinggal. Setelah itu dia baru akan mengusahakan hal yang lain untuk mereka. Tanpa sepengetahuan orang tua, Adi bahkan sampai meminjam uang pada Bos di toko dan beberapa teman. Sayangnya hingga hampir dua minggu uangnya belum terkumpul meski sudah mencari pekerjaan tambahan. Sungguh kenyataan hidup yang pelik, di tengah usaha keras itu Adi tidak tahu hal besar sedang mengarah padanya. Malam itu, ketika ia baru sampai di rumah dengan segala lelah, pak Suro datang membawa tagihan bersama dua preman dan juga kemarahan.
“Selamat malam!” Suara seorang lelaki diikuti ketukan pintu bebrapa kali.
Di dalam Adi dan ibu saling bertatapan. Suasana yang semula biasa jadi mencekam teriring pecahnya tangisan ibu. “Ibu, aku yang temui pak Suro.” Adi berkata tanpa ragu sebelum bergegas keluar.
Malam itu hati Adi bulat sempurna. Apapun yang ia lakukan adalah demi orang tuanya. Tidak ada sedikit pun rasa takut, bahkan kesungguhan cinta membuat jemarinya tidak bergetar sedikitpun meski sadar pak Suro sangat pemarah dan dua preman yang datang bersamanya sangat kuat.
“Kau sudah tahu tujuan kami Nak! Sekarang panggil orang tuamu.”
Adi tersenyum. “Sekarang ini saya yang menggantikan bapak yang tengah sakit. Saya mengerti benar anda meminta hak anda dan memang kewajiban kami untuk membayar.”
“Bagus kalo kau sudah tahu! Bayar sekarang atau kemasi barang kalian! Telat hampir empat bulan tanpa ada itikat baik untuk membayar adalah hal yang tidak baik jika dibiarkan.”
Adi terdiam, ia mencoba tahu diri dan menyadari situasinya. Keluarganya memang salah, pak Suro marah dengan alasan yang benar, ia tidak boleh marah apa lagi benci. “Saya berterimakasih atas kebaikan Bapak. Saya tahu kami yang salah.”
Adi menatap kearah pak Suro dengan tatapan teduh. “Saya yakin Bapak tahu apa yang terjadi pada keluarga kami. Soal Bapak saya yang jatuh dan ibu saya yang sakit. Saya lelaki, Pak, maka saya menjaminkan kebanggaan itu untuk meminta keringanan sedikit lagi. Malam ini saya hanya bisa bayar setengahnya. Bantu saya berbakti pada orang tua saya, Pak.” suara Adi merendah.
“Omong besar!” kata Pak Suro dengan tatapan tajam dan geram. “Kau pikir aku akan merasa iba?”
Adi tak bergeming. Tatapannya tak berubah, teduh dan penuh pengertian. Perasaannya juga tidak diliputi rasa benci sedikitpun. “Kalo begitu terima kasih, Pak.” Adi mengangguk, hatinya penuh kelegaan meski batinnya berkecamuk menatap masa depan.
Pak Suro mengalihkan pandang ketika tangan Adi menjulur mengajak berjabat tangan. Selama ini pemilik kontrakan itu belum pernah bertemu pemuda seperti Adi. Diam-diam ada rasa kagum mekar di dasar hatinya. Berbagai pertimbangan muncul secara kilat hingga pada detik kesekian, ada sesuatu yang berubah dalam pemikirannya.
“Berikan semua uangmu. Jika kau lelaki, antarkan setengahnya minggu depan.” Pak Suro berkata sembari menjabat tangan Adi.
Adi pun tersenyum mendengar ucapan Pak Suro. Malam itu, cinta Adi pada orang tuanya mekar seperti sekuntum bunga.