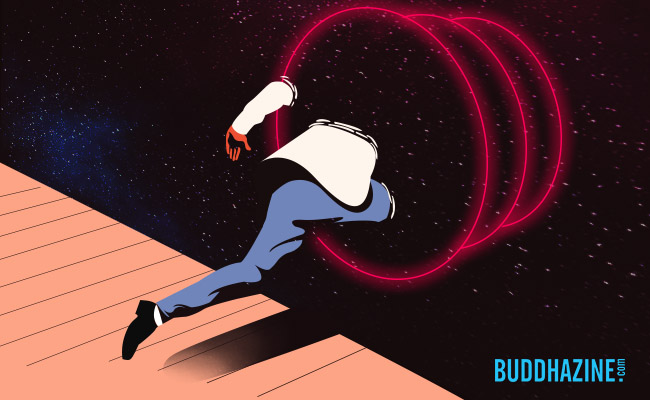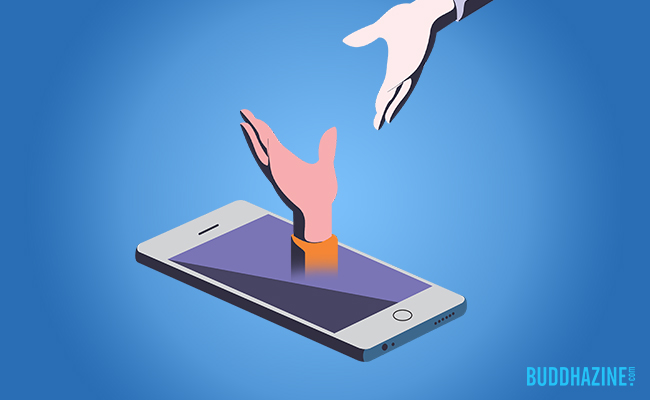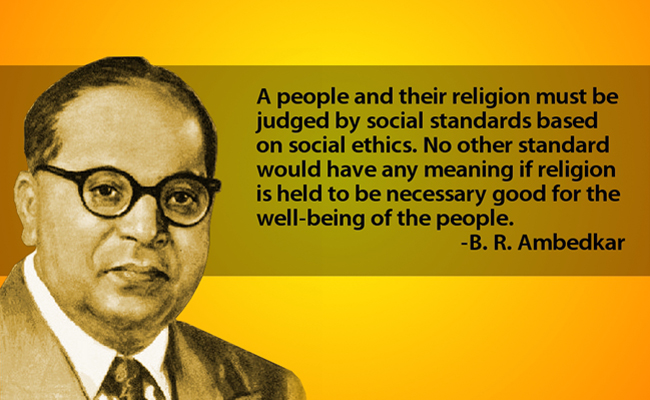“Mengapa kematian itu terasa begitu final?” Itulah yang terlintas di pikiran sewaktu saya menghadiri upacara kremasi saudara di Krematorium Nirwana, Marunda, pada tanggal 12 April lalu. Saya duduk termenung memikirkan hal itu di antara para pelayat yang juga datang menghadiri upacara tersebut.
Tidak banyak memang pelayat yang datang pada upacara itu. Namun demikian, nuansa duka yang kental tetap terasa mengisi ruang krematorium tersebut. Apalagi, sewaktu para pemimpin upacara mulai menyanyikan lagu perpisahan, air mata terlihat menggenang di wajah beberapa anggota keluarga yang ditinggalkan.
Sesaat saya merenungkan betapa fananya kehidupan ini. Pada akhirnya, semua kehidupan akan “selesai” begitu kematian datang. Semua yang telah diraih dalam kehidupan ini, seperti reputasi, kekayaan, dan pangkat, ujung-ujungnya akan ditinggalkan jua jelang kematian. Makanya, bagi sebagian orang, kematian bisa bermakna “akhir” dari segalanya!
Kisah Kisagotami
Sewaktu merenungkan kematian, pikiran saya pun “terbang” pada kisah Kisagotami. Kisah itu berawal ketika Kisagotami mendapati anaknya terserang penyakit keras. Ia mengupayakan pelbagai pengobatan untuk menyembuhkan anaknya, tetapi anak itu pada akhirnya meninggal dunia.
Kisagotami tak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia bersikukuh bahwa anaknya masih “hidup”. Makanya, ia membawa-bawa jenazah anaknya ke sejumlah tabib yang dianggap mampu menyembuhkan anaknya itu. Namun, semua tabib yang didatanginya “angkat tangan”. Mereka tak sanggup mengobati anaknya.
Di tengah kekalutan, Kisagotami bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya di sepanjang jalan tentang seseorang yang bisa mengobati anaknya. Setelah bertanya ke sana-ke sini, akhirnya seseorang menyarankan supaya ia datang menemui Buddha karena mungkin saja Buddha bisa menyembuhkan anaknya.
Kisagotami pun datang menghadap Buddha. Dengan bercucuran air mata, ia menceritakan semua peristiwa pahit yang sudah dilaluinya. Setelah selesai, sambil memperlihatkan jenazah anaknya, ia memohon, “Buddha yang terbekahi, mohon sembuhkanlah anakku.”
“Engkau telah datang ke orang yang tepat, Kisagotami!” kata Buddha. “Untuk mengobati anakmu, bawakanlah Aku segenggam biji lada yang diperoleh dari seseorang yang keluarganya belum pernah meninggal dunia.”
Kisagotami menyanggupi permintaan tersebut lantaran ia merasa mudah mendapatkan biji lada di rumah penduduk yang dikunjunginya. Makanya, kemudian, ia pun mengetuk pintu rumah seorang warga.
“Tuan yang baik, bisakah engkau memberiku segenggam biji lada?”
“Ya tentu saja.”
“Namun, apakah di rumah ini ada keluargamu yang belum pernah meninggal dunia?”
“Tidak ada. Keluargaku ada yang telah meninggal dunia.”
“Baiklah. Terima kasih, tuan yang baik.”
Kisagotami berlalu tanpa mengambil lada itu dan mengetuk pintu lainnya. Lagi-lagi ia pun mendapat jawaban yang sama. Setelah seharian mencari, ia akhirnya menyadari bahwa kematian itu bisa terjadi tak hanya kepada anaknya, tetapi juga anggota keluarga orang lain.

Mengungkapkan Kesedihan
Seperti Kisagotami, kita bisa belajar memahami bahwa kita tidaklah “sendirian” sewaktu mendapati ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Orang lain pun mengalaminya. Maka, dengan merenungi hal tersebut, perasaan “kehilangan” akan jauh lebih berkurang, biarpun itu mungkin tak bisa “menghapus” semua kesedihan di hati!
Selain itu, kita juga dapat mengurangi kesedihan dengan mengungkapkannya secara wajar. Buddha tidak pernah melarang umatnya untuk mengekspresikan kesedihan atas “kepergian” orang terkasih. Menurut Buddha, ratap tangis yang diperlihatkan adalah sesuatu yang wajar sebagai reaksi atas munculnya kelekatan terhadap orang tersebut.
Oleh sebab itu, ketika umatnya sedang dirundung duka akibat kematian orang tercinta, alih-alih mencermahi atau memarahi, Buddha justru menyampaikan kata-kata yang menenangkan, seperti yang pernah diucapkan kepada Visakkha sewaktu cucunya meninggal dunia. Kata-kata itu menjadi semacam “vitamin” untuk hati yang sedang hancur, sehingga seseorang yang menyimaknya dapat menyudahi kesedihannya segera.
Bagi sejumlah orang, kematian adalah sebuah “garis finish”, kalau orang yang bersangkutan menyamakan hidup ini dengan “lari maraton”. Jadi, kalau ada anggota keluarga yang mencapai “garis finish” tersebut, selesailah sudah semuanya. Maka, bagi orang tersebut, kematian terasa begitu final. Namun demikian, jika kita memandangnya sebagai sesuatu yang “jamak” terjadi kepada setiap orang, kesedihan atas kematian orang tercinta bakal lebih cepat “reda”, sehingga orang itu bisa punya tenaga untuk bangkit dari kesedihan tersebut.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara