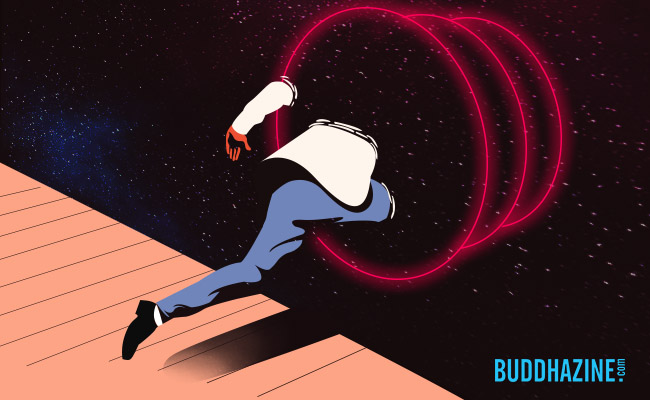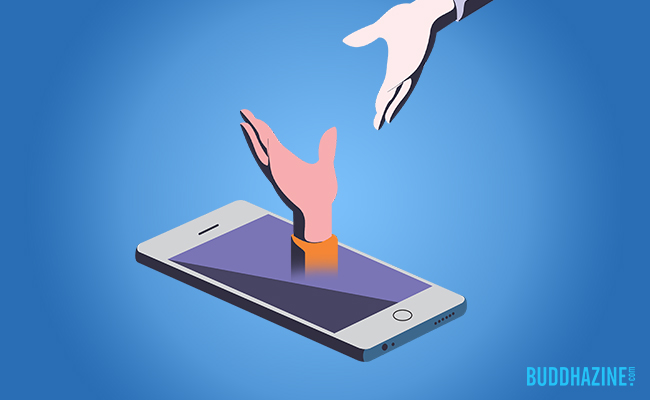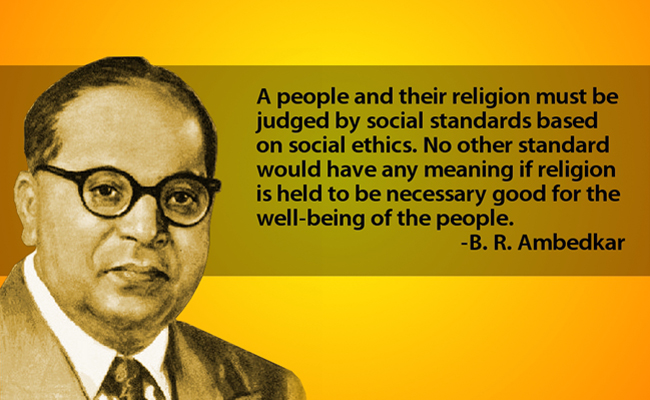Siapakah orang yang paling dibenci banyak orang di dunia ini? Setelah saya amati dan renungkan, jawabannya adalah “diri sendiri.”
Sebagai umat Buddha yang berlatih cinta kasih dan selalu mendoakan semua makhluk bahagia di setiap penutup setiap acara, ironisnya saya punya ketidaksukaan besar pada diri sendiri. Tiap kali saya salah, saya berkata pada diri sendiri, “Kok begitu gampang saja, kamu bisa salah sih?” Tiap kali ada penolakan melakukan sesuatu, saya berkata pada diri sendiri, “Mengapa tidak bisa kamu kuatkan tekadmu untuk melakukan itu. Kok kamu gitu sih?”
Dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain, saya pun mengamati sindrom ini juga ada pada teman-teman dan orang-orang yang berusaha berjalan di jalan baik. Seorang teman yang membantu satu acara di panti asuhan yang anak-anaknya hiperaktif malah meminta maaf karena mengambil inisiatif membantu menjadi MC. Padahal kami semua sangat berterima kasih karena dia mengendalikan situasi yang kacau balau sehingga menjadi nyaman, tapi yang dia ingat sesudah acara bukanlah kebaikannya, justru bahwa mungkin dia merasa salah karena mengambil alih tugas MC tanpa izin.
Saya mencari jawaban di buku-buku, di ceramah-ceramah. Saya juga tanyakan pada orang-orang yang saya hormati. Orang-orang memberi jawaban yang praktis, misalnya kamu harus melakukan ini, itu dan sebagainya; atau jawaban filosofis kamu musti menerima karma, dan lain-lain.
Saya ikuti sebisanya. Saya fangsen, saya berbuat baik pada orang, saya meditasi cinta kasih agar karma saya meringan. Tapi rasa sakit dan berat di hati tidak menghilang. Muncul suatu vonis: “Saya tidak bisa jadi orang baik.”
Saya bertanya, “Apa yang salah dengan latihan saya?” Saya tahu dan yakin ajaran Buddha sudah benar, saya sudah bertemu dengan guru yang tepat, dan saya punya kalyanamitta-kalyanamitta yang sangat baik. Apa yang belum saya lakukan sesuai petunjuk Buddha?
Suatu hari, seorang sahabat baik menyakiti hati saya secara tidak sengaja. Secara logika saya tahu dia tidak bersalah, bahwa kami hanya beda cara menghadapi suatu situasi; tapi sanubari terdalam saya tidak bisa memaafkan dia. Mengetahui diri saya tidak bijak, saya melakukan meditasi pemaafan agar mampu memaafkan dia. Setelah beberapa hari, saya cukup berhasil, hanya tersisa sedikit sisa ketidaksukaan.
Tetapi saya merasa, “Mengapa saya tidak mampu melepaskan perasaan negatif ini seluruhnya, padahal saya tahu bahwa ini tidak baik, dan saya sudah berusaha.” Saya merasa tidak puas pada diri sendiri.
Tiba-tiba saya teringat pada satu saran Buddha dalam Majjhima Nikaya 21: Perumpamaan Gergaji (Kakacūpama Sutta). Saran ini sering saya gunakan untuk memaafkan orang lain, tapi apakah ada makna yang belum saya sadari?
“Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan yang merugikan; ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran penuh cinta-kasih atau dengan kebencian di dalamnya.
Di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian: ‘Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat; kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta kasih, tanpa kebencian di dalamnya. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih; dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk.’ Demikianlah kalian harus berlatih, para bhikkhu.”
Melingkupi orang itu dengan pikiran penuh cinta-kasih!
Tiba-tiba saya melihat masalah saya. Saya bersedia dan berusaha memaafkan teman saya itu, saya bagikan cinta kasih padanya; tapi pada diri sendiri, saya bagaikan sipir penjara yang keras. Setiap kali ada pikiran atau perasaan negatif (yang tidak saya sukai karena saya berusaha menjadi orang baik, seorang Buddhis sejati), saya memukul diri saya agar patuh lagi kembali ke jalan “Buddhis”. Tapi saat itu saya lupa, bahwa mendasari semua doktrin ajaran, ajaran Buddhis intinya adalah ajaran penuh cinta kasih menerima momen ini, bagaimanapun situasinya, dengan lembut.
Dengan berupaya mengikuti doktrin-doktrin Buddhis yang lain, saya telah menyalahi pondasi Dhamma ini.
Dikatakan dalam sutta itu, “Engkau melingkupi orang itu dengan pikiran penuh cinta kasih.”
Oh, saya lupa! Saya pun orang! Saya pun berhak dan patut mendapatkan cinta kasih.
Saya mulai praktekkan itu pada diri sendiri. Saya mulai melihat ada si Ditu yang ketakutan, yang butuh penerimaan, yang sedang menderita. Ditu ini sudah putus asa. Dia merasa dia takkan bisa jadi orang baik. Dia merasa diri sebagai Buddhis yang gagal.
Jadi begitu pikiran mengkritik tentang si Ditu muncul, saya langsung memotongnya, dan saya rilekskan ketegangan di pikiran dan kepala, saya lingkupi Ditu dengan cinta kasih dan tersenyum. Kebahagiaan kecil biasanya muncul, ada sedikit kelegaan. Lalu secara otomatis cinta kasih ini meluas ke sekitar saya.
Ini bisa terjadi saat berjalan, atau saat bekerja. Terkadang saat menyetir. Kapan pun saya bisa memejamkan mata selama 10 detik untuk memberikan cinta kasih ini pada diri sendiri, saya berikan. Jika tidak bisa memejamkan mata, misalnya sedang menyetir, maka saya berikan tanpa memejamkan mata.
Suatu hari, sesudah melakukan ini dua-tiga minggu, tibalah saat Kathina. Saat itu, dalam suasana luhur itu, saya menutup mata dengan rileks menikmati suasana akan melakukan persembahan itu. Tiba-tiba muncul lagi suatu suara hati yang mengkritik diri, karena saya tidak mempersembahkan jubah, hanya mempersembahkan peralatan sehari-hari. Lagi-lagi, melihat kritik diri ini, saya memotong pembicaraan internal ini, saya rilekskan ketegangan di pikiran dan kepala saya, lalu saya lingkupi diri dengan rasa cinta kasih dan welas asih. Tiba-tiba di dalam hati muncul satu kalimat, “Kamu itu ok loh. Sebenarnya kamu itu sudah cukup baik.”
Ini bukanlah pengetahuan yang sombong, melainkan suatu penerimaan tulus pada kondisi saya. Momen singkat itu adalah titik balik saya, muncul suatu kelegaan besar. Saya yang selama ini merasa diri jahat, pada titik itu melihat bahwa saya akhirnya berjalan di Jalan Buddha, saya pantas menjadi murid Buddha.
Tapi kekesalan terhadap teman itu belum sepenuhnya hilang. Hingga suatu hari, saya bertemu seorang teman lain, yang terus-menerus memprovokasi saya. Saya terus-menerus memancarkan metta padanya dan diri sendiri saat kami berbincang; tapi ketika dalam perjalanan pulang, saya melihat bahwa pikiran saya sudah mengetat dan mengulang-ulang percakapan kami tadi. Saya bahkan mengeluhkan “betapa anehnya teman saya itu” ke suami saya.
Guru saya, Bhante Vimalaramsi, selalu mengingatkan, “Jika ada pikiran yang berulang-ulang muncul, itu artinya kamu melekat padanya.” Jadi saya sadari saya telah melekat pada pemikiran saya. Saya lakukan lagi langkah-langkah itu, setiap kali pemikiran itu muncul, saya potong dengan lembut, saya rilekskan ketegangan di pikiran dan kepala, dan saya berikan kelembutan padanya.
Sesudah melakukan itu beberapa jam, yang artinya saya sungguh sangat melekat pada pemikiran itu, tiba-tiba ketegangan itu semua hilang mendadak. Mendadak semua rasa kesal pada teman itu hilang, kata-kata yang merasa dia aneh melebur. Tiba-tiba saya melihat penderitaannya, bahwa dia mungkin perlu orang untuk mendengar, tapi ternyata saya justru tidak mendengarkan dia juga. Saya jadi bertekad untuk mendengarkan dia baik-baik. Rasa menyalahkan berubah secara otomatis menjadi welas asih pada penderitaannya.
Tiba-tiba saya sadari pula, kekesalan lama pada sahabat saya yang lain, yang berbulan-bulan tidak bisa saya lepaskan, juga menghilang.
Saat itu, saya mengalami kondisi mental yang begitu lembut. Saya mengalami sendiri kondisi di mana ketika pikiran lembut, tidak ada sesuatu pun yang dapat melukainya. Secara otomatis muncul pemahaman: “Jika kamu terluka oleh orang lain, itu karena permukaanmu keras. Sehingga kekerasan mereka menggoresmu. Jika permukaanmu bagaikan bantalan lembut, maka sekeras apa pun mereka, kamu takkan terluka dan mereka akan mendarat dengan lembut tanpa cedera. Kita berdua selamat.”
Semua ini dialami sendiri secara langsung, secara alami. Tidak ada proses berpikir saat itu. Pengetahuan dan pemahaman muncul sendiri ketika pikiran cukup lembut. Tapi pengalaman ini mengkonfirmasi teori-teori yang pernah saya dengarkan, baca atau renungkan tentang Dhamma. Konfirmasi pengalaman sendiri sudah menambah keyakinan saya, tanpa perlu diyakinkan oleh penceramah mana pun atau guru mana pun, bahwa ajaran Buddha “menerima kondisi saat ini dengan lembut” adalah cara pamungkas untuk hidup bahagia dan untuk mengizinkan munculnya pengetahuan mendalam.
Saat itu, kita hidup sesuai instruksi Buddha: “Hidup di momen kini dengan penuh penerimaan.” Penerimaan yang alami, tanpa paksaan, tanpa upaya keras.