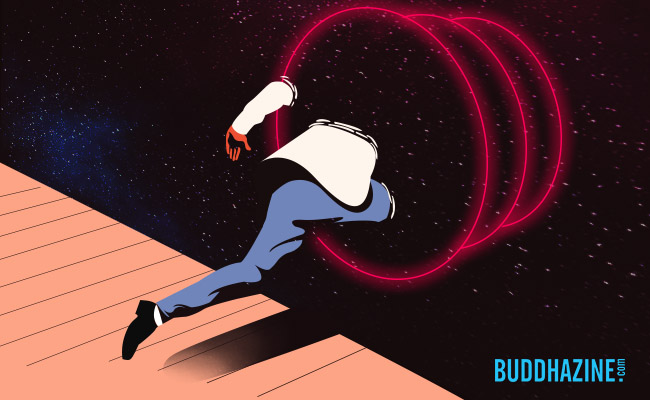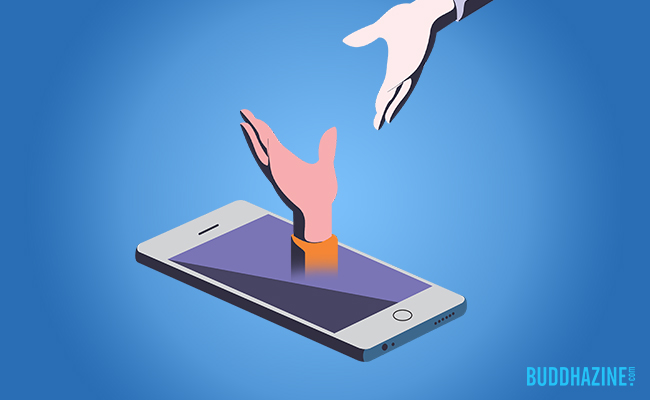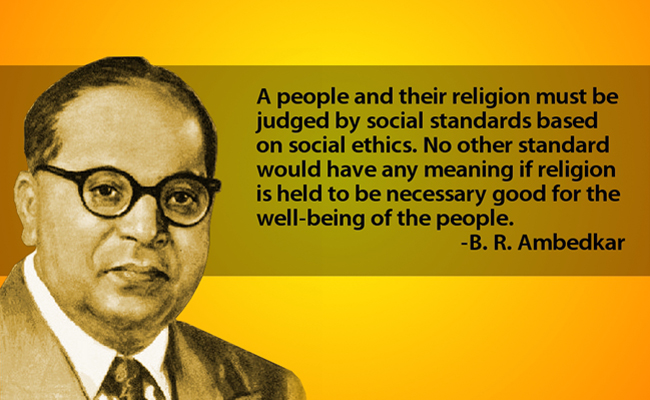Oleh: Andreian (An)
Malam yang sunyi, aku duduk di dekat pohon kelapa sembari menikmati panorama langit. Saat ini tengah purnama, rembulan terlihat bulat sempurna menampakan diri sambil bergelayut di atas laut. Mungkin jika aku pergi ke bibir pantai, ombak sedang pasang sekarang.
“Kau sangat menyukai rembulan ya?” suara Didik terdengar tepat di belakangku.
“Ya, aku sangat menyukai rembulan.” Aku tidak berbalik. “Apa kau tahu bagian hitam pada wajah purnama itu membentuk apa?”
“Bagiku itu menyerupai dino saurus, menurutmu?”
“Kelinci, coba perhatikan,” aku menunjuk ke arah bulan, “bagian bercabang yang mungkin kau anggap sebagai rahang sebenarnya adalah telinga, sedangkan bagian besarnya adalah badan dan kaki. Lihatlah, kelinci itu sedang duduk.”
“Benar juga ya?” kata Didik yakin.
“Gambar itu adalah buatan raja para dewa sebagai ungkapan kagum terhadap seekor kelinci yang sengaja masuk ke dalam api agar dapat memberikan tubuhnya pada seorang petapa kelaparan.”
“Cerita yang bagus, aku jadi penasaran apa yang bisa kita berikan esok hari.” Didik memang pintar bicara dan pandai membujuk. “Sebaiknya kau segera tidur agar esok dapat melakukan hal-hal besar sebagaimana yang kelinci itu lakukan.”
Aku bangkit berdiri dan berbalik arah dengan gerakan yang gesit. Beberapa detik aku dan Didik berhadapan, mata lelaki itu berbinar-binar. “Baiklah,” kataku singkat sebelum bergegas masuk ke dalam tenda.
—————
Sekitar pukul enam pagi. Aku, Didik, dan tiga orang anggota tim yang lain sudah mulai bersiap. Hari ini tugas kami adalah membagi alat tulis dan senyuman yang manis. Pemulihan pasca bencana tidak hanya soal bangunan rumah dan logistik. Menjaga keceriaan anak-anak dan semangat belajar mereka juga penting supaya trauma tidak berkepanjangan.
Perjalanan kami lakukan dengan menggunakan mobil bak terbuka berukuran sedang sekitar satu jam kemudian. Sepanjang jalan aku bisa melihat ke semua arah dengan leluasa. Ya, sebuah keleluasaan yang memilukan, sebab apa yang kulihat adalah deretan rumah yang sudah rata dengan tanah. Sesekali hatiku seperti tersentak ketika melihat orang-orang tengah beraktivitas di sekitar tenda darurat. Aku jadi ingin pulang dan rindu pada keluarga.
“Lina, kau melamun terus.” Lagi-lagi Didik menegurku.
“Eh, iya Dik. Anu, enggak kok, aku hanya sedang melihat ke sekitar.”
“Hahaha, iya-iya, ngomong-ngomong perjalanan kali ini cukup jauh. Kita akan menuju bagian timur soalnya, jadi butuh beberapa jam.”
“Tidak masalah.” Aku menjawab dengan yakin dan segera kembali mengamati pemandangan. Didik juga memilih diam.
Tanpa terasa matahari sudah semakin jumawa. Cahayanya terasa panas menyengat kulit dan menyerang tenggorokan. Sedikit demi sedikit bekal air mulai berkurang, perut yang lapar karena belum sarapan juga menjadi masalah tersendiri pada perjalanan kali ini. Beruntung, Didik yang menjadi pemimpin kelompok tanggap dengan suasana. Ketika mobil telah melewati area pemukiman ia meminta Agung menghentikan mobil.
“Gung, berhenti di depan. Kita sarapan dulu.”
Agung mengacungkan jempol, mobil pun menepi dan berhenti di bawah pohon kelapa.
“Tere, Niken, keluarkan bekal kita.” Didik memberi instruksi yang duduk di depan menemani Agung.
“Baik,” jawab mereka serentak.
Kami pun akhirnya makan di bawah pohon kelapa. Bekal nasi dan lauk seadanya terasa enak dengan tambahan sambal yang pedas. Suasana pantai yang asri juga menambah nafsu makan.
“Pedes,” Pekik Niken, “air-air!”
Tere sigap, “Ini.” Memberikan botol minum.
Semua orang tertawa melihat Niken. Bukan karena mereka tidak kasihan, tetapi ekspresi Niken memang sangat lucu. Ia terus mengipas mulutnya dengan tangan sembari minum beberapa kali.
“Hahaha bukannya kamu tidak suka pedes?” Didik berbicara, mengunyah, dan tertawa secara bersamaan.
“Diem kamu Dik.” Niken terlihat kesal.
“Hahaha sudah ayo segera selesaikan, kita harus bergegas.” Aku mencoba melerai meski juga ikut tertawa.
“Haha iya-iya baik.”
Perjalanan pun berlanjut beberapa saat kemudian. Aku dan Didik kembali harus menghadapi paparan sinar matahari karena duduk di belakang. Beruntung kami sedikit teralihkan dengan pemandangan laut di sebelah kiri dan perbukitan di sisi kanan.
“Didik!” Agung tiba-tiba menghentikan laju mobilnya.
“Ada apa, Gung?”
“Kita sudah sampai. Perjalanan berikutnya harus kita tempuh dengan berjalan kaki.”
Aku mendengar percakapan dua lelaki itu sembari melihat situasi. Mobil berhenti tidak jauh dari persimpangan jalan kecil menuju ke suatu perbukitan. Sebenarnya ukuran jalan itu memungkinkan untuk dilewati mobil, sayangnya gempa telah membuat kerusakan yang cukup parah. Beberapa bagian jalan terlihat patah dan terpisah dengan jarak hampir satu meter. Sangat tidak memungkinkan untuk dilewati dengan mobil.
“Ya sudah ayo kita berangkat!” Didik terdengar bersemangat.
“Baik!” jawab kami serentak.
Didik pun membagi bawaan, jumlah kotak barang yang tanpa disengaja berjumlah sama dengan anggota membuat permasalahan ini lebih sederhana.
“Ayo mulai berjalan.” Didik memulai di depan, kami mengikutinya dengan semangat.
Berjalan kaki di bawah terik matahari sembari membawa barang ternyata cukup menguras tenaga, belum lagi jarak tempuh yang cukup jauh dan jalanan yang terjal. Rasa lelah kehausan segera menyerang kami dengan membabi buta. Aku sendiri memilih untuk menahan dahaga dan tidak meminta air minum. Teringat kisah kelinci aku berharap bisa membantu yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Lagi pula aku masih kuat untuk bertahan beberapa lama lagi tanpa air.
“Istirahat dulu.” Didik memang ketua yang mampu membaca situasi. Kami pun beristirahat sejenak dan minum secukupnya. Bekal air sudah hampir habis saat itu.
“Ayo bergerak lagi.” Kali ini Agung yang mengusulkan.
“Yap.” Semua orang pun berdiri melanjutkan perjalanan.
Butuh sekitar satu jam hingga kami sampai di sebuah jembatan. Di sana aku menyadari bahwa kemarau memang sedang perkasa hingga sungai sampai kering. Dari tempat kami berdiri, terlihat puluhan tenda pengungsian. Semangat kami kembali melejit meski masih begitu kehausan. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah tenda posko.
“Selamat siang.” Didik memberi salam sembari berjalan masuk.
Aku tertegun ketika melihat situasi di dalam tenda. Hanya ada dua penjaga di sana, mereka terlihat berbaring dengan wajah yang letih dan lesu. Barang-barang di dalam juga tidak banyak.
“Siang, Kak.” Dua orang itu bangkit dengan ceria.
“Kok cuma berdua?” tanya Agung.
“Anu Kak, sebagian relawan sedang mengambil logistik di pusat.”
“Loh bukanya sudah ada yang bertugas mengantarkan?” Didik keheranan. “Niken, tadi memang tidak ada daftar logistik yang harus kita kirimkan ke sini kan?”
“Tidak Dik, aku sudah pastikan kok.”
Didik terlihat berpikir, “Maaf ya Dek, kami adalah relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu kami bertanggung jawab penuh pada pembagian alat tulis dan buku-buku untuk korban pasca gempa. Memang kami juga sering membantu mengirim logistik, tetapi hanya jika posko utama menitipkan aja.”
“Iya, Kak tidak masalah. Di sini memang beberapa kali ada hambatan kok. Oh iya, silakan duduk. Barang kalian letakkan dulu, Kak. Jika mau membagi sendiri nanti kami panggilkan anak-anak dulu. Kalian istirahat saja.”
“Baiklah.”
“Kak, saya haus.” kata salah seorang pemuda.
Kami saling menatap seolah meminta kepastian satu sama lain. Kali ini Didik tidak segera memutuskan.
“Ini minum.” Kuserahkan botol yang kupegang dengan yakin. Satu botol lagi juga diserahkan Niken pada pemuda yang satunya. Saat itu melihat orang minum terlihat begitu menggiurkan.
“Makasih Kak, kami kumpulkan anak-anak dulu.”
—————–
Berada di tenda meski tidak terpapar matahari terasa begitu gerah. Dahaga yang kami pun rasakan semakin menggila. Kerongkongan kering, sementara keringat terus bercucuran hingga tubuh ini kehilangan banyak tenaga.
“Kak anak-anak sudah kumpul, mereka di luar.” Kata salah satu anak.
“Baik,” Didik terdengar bersemangat, “ayo teman-teman kita tuntaskan misi kali ini.”
Entah mengapa Didik selalu bisa menggugah semangat orang-orang disekitarnya. “Baik!” teriak kami serentak.
Dengan sisa tenaga kami keluar membawa barang yang akan dibagikan. Senang rasanya melihat puluhan anak datang dan menunggu sembari berteduh di bawah pohon yang rindang.
“Anak-anak!” Niken menyapa dengan ceria.
“Iya Kak!” jawaban serentak itu menggetarkan jiwaku, mereka tampak antusias dari cara pandang yang berbinar-binar. Rasanya aku ingin berteriak untuk menyemangati mereka, tetapi dahaga membuatku tidak mampu melakukannya. Ini karena sejak di jalan aku hanya minum dalam jumlah yang sedikit sehingga membuat dehidrasi.
“Ayo siapa yang mau alat tulis dan mendengar cerita?” Tere menawarkan sembari tersenyum.
Kali ini aku tertegun, sebab aku menyadari binar mata mereka berubah sekalipun tangan mereka mengacung dan bibir mereka berkata mau. Aku yakin mereka juga merasa lapar dan haus sebab bibir mereka pun berwarna pucat dan kering.
Meski menyadari banyak yang kecewa, alat tulis tetap dibagikan setelah mereka duduk melingkar dengan rapi. Tere dan Niken mulai bercerita tentang kisah kelinci yang semalam kuceritakan pada Didik. Anak-anak terlihat mendengar walau kurang antusias. Ada harapan kekecewaan mereka akan sedikit berkurang.
Aku sendiri ikut duduk melingkar di antara mereka. “Kak, tidak ada air atau makanan ya?” Salah seorang anak di sebelah kananku bertanya.
“Belum ada, Dik.” Aku menjawab jujur meski hatiku terasa hancur.
Anak itu hanya mengangguk pasrah dan mulai melamun.
“Kak?” kali ini anak di sebelah kiriku yang bertanya.
“Iya, Dik?” Aku mencoba tersenyum.
“Kelinci itu sangat baik ya, Kak? Dia mau mengorbankan diri demi membantu yang membutuhkan.” Gadis itu tersenyum.
“Iya, Dik. Kau juga harus senang berbagi, ya.”
“Baik, Kak.”
Ah senyum anak itu benar-benar indah, binar matanya yang polos juga sangat cantik, “Namamu siapa?”
“Lia Kak, lengkapnya Mulia.”
Aku kembali tersenyum.
“Kak, sebentar ya.” Lia segera pergi tanpa menunggu jawabanku.
Tubuh yang semakin lemas membuatku memilih kembali melihat Tere dan Niken beraksi. Barangkali menyaksilan mereka bisa menjadi pengalih dari rasa haus yang semakin mencekik. Sayangnya tubuh ini seperti mencapai batas. Pandangan mata mulai kabur, seluruh rongga mulut terasa lengket, kepala pusing, dan jantungku berdebar begitu kuat. Aku mencoba mengganti posisi dengan meluruskan kaki dan meletakkan kedua telapak tangan di belakang sebagai tumpuan.
“Kak ini buatmu.” Lia tiba-tiba datang dan menyodorkan segelas air mineral. “Kami kemarin dapat dua, aku baru menghabiskan yang satu gelas. Kakak haus, kan?”
Aku bingung ingin berkata dan berbuat apa.
“Ini kak terimalah.” Lia meyakinkanku sekali lagi dengan sebuah senyuman pada bibir keringnya itu.
Aku tersenyum, belum ada jawaban yang keluar dari bibirku. Justru air matalah yang kemudian mulai mengalir pada pipiku.
Aku memeluk anak itu erat, semua orang di sana menatap kami lekat-lekat.
“Lia, kamu memang berhati sangat mulia. Seandainya aku raja dewa, pasti kugambar wajahmu pada permukaan bulan purnama.” kataku dalam hati.