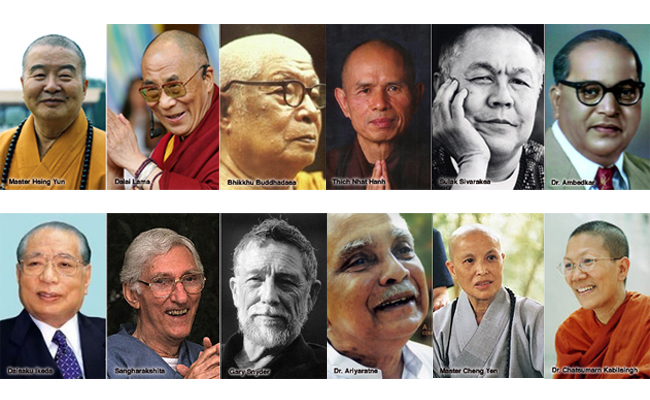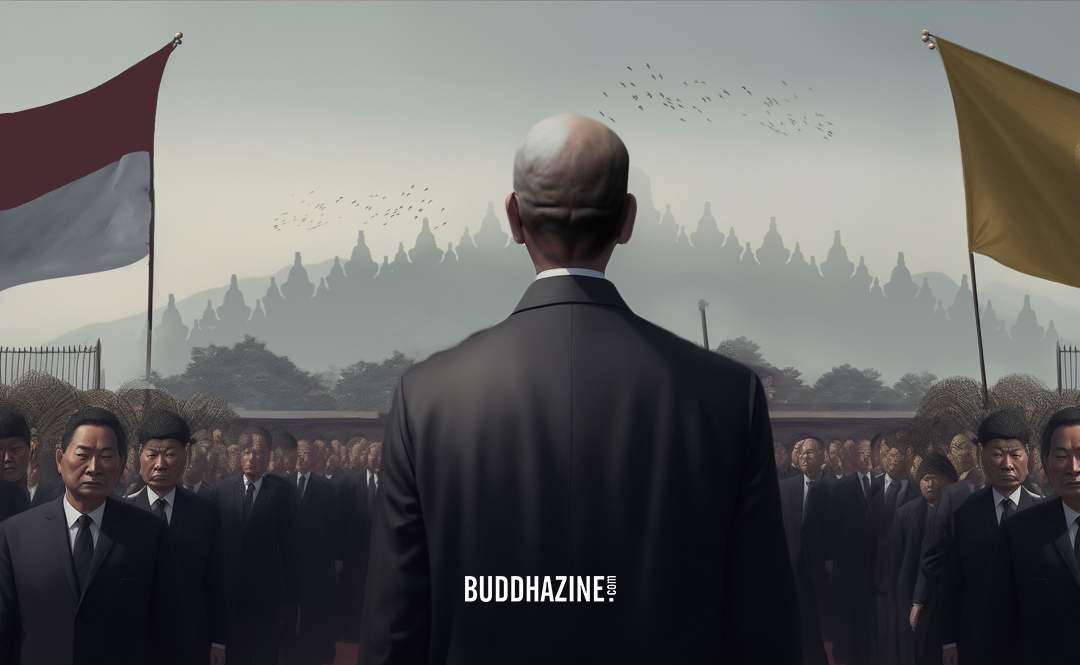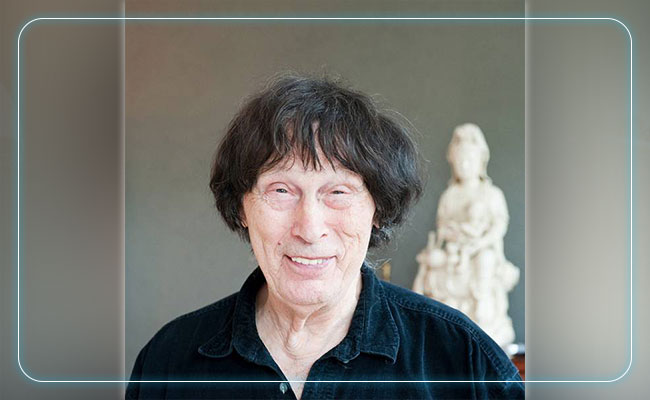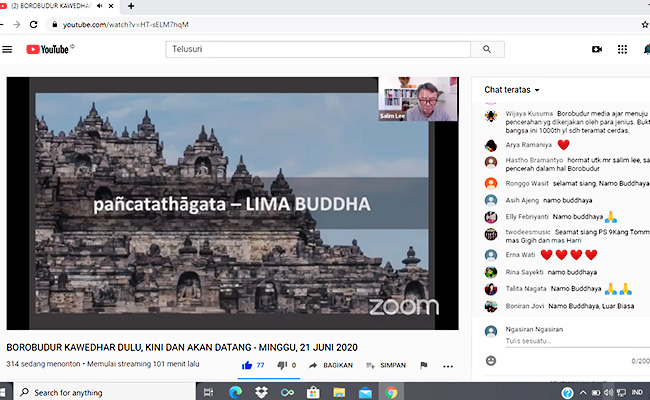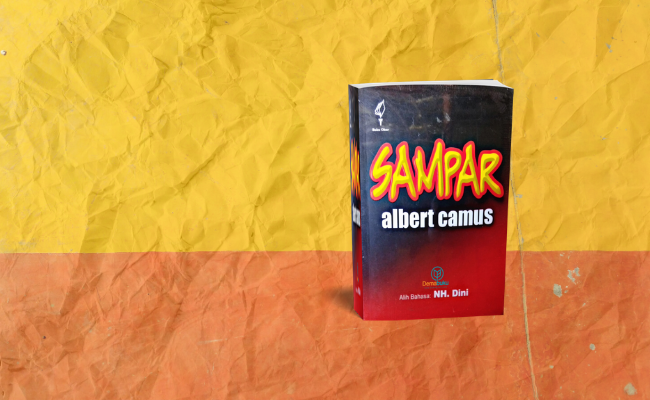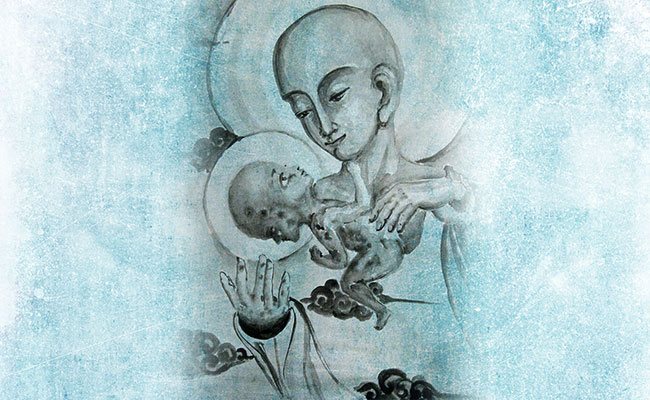Ketuhanan menjadi topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini di Tanah Air. Ini sehubungan dengan opini yang berkembang bahwa tidak ada Tuhan dalam agama Buddha, sehingga dianggap tidak sesuai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Kongres pertama dari Dewan Sangha Buddhis Dunia (WBSC: World Buddhist Sangha Council), Colombo, Sri Lanka, pada 27 Januari 1967 secara aklamasi telah menyepakati 9 poin. Yang nomor tiga adalah tidak meyakini bahwa dunia ini diciptakan dan diatur oleh Tuhan. Inilah yang membuat agama Buddha menjadi agama yang “berbeda” dibanding agama-agama pada umumnya.
Theravada
Namun agama Buddha sebenarnya tetap mengakui adanya konsep Ketuhanan. Aliran Theravada yang kadang dianggap tidak ber-Tuhan mengacu pada khotbah Buddha yang terdapat dalam Kitab Udana VIII, yang berbunyi:
“Para bhikkhu, ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak. Para bhikkhu, bila tidak ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka tidak ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan pemunculan dari sebab yang lalu.
Tetapi para bhikkhu, karena ada Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan pemunculan dari sebab yang lalu.”
Karena itu bisa dikatakan Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dalam agama Buddha yakni, “Suatu yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan, Yang Mutlak”, meski tidak dikategorikan sebagai pencipta dan pengatur semesta. Ketuhanan dalam agama Buddha adalah sesuatu yang dalam bahasa Jawa disebut tan kena kinaya ngapa atau tidak dapat apa-apakan/disiapa-siapakan.
Dan bila harus menyebut “merk” atau nama, di Indonesia ada konsep Sang Hyang Adi Buddha, konsep ketuhanan yang dicetuskan oleh Y.M. Ashin Jinarakkhita yang hingga saat ini masih digunakan oleh Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia. Istilah ini tidak terdapat dalam Tipitaka (kanon Pali), namun terdapat dalam kitab Sanghyang Kamahayanikan, sebuah kitab Buddhis Jawa kuno.
Adi Buddha
Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1988), Adi Buddha dan tradisi yang menggunakan istilah ini dijelaskan sebagai berikut:
“Adi‐Buddha adalah salah satu sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha. Sebutan ini berasal dari tradisi Aisvarika dalam aliran Mahayana di Nepal, yang menyebar lewat Benggala, hingga dikenal pula di Jawa. Sedangkan Aisvarika adalah sebutan bagi para penganut paham Ketuhanan dalam agama Buddha. Kata ini berasal dari ‘Isvara’ yang berarti ‘Tuhan’ atau ‘Maha Buddha’ atau ’Yang Mahakuasa’, dan ‘ika’ yang berarti ‘penganut’ atau ‘pengikut’.”
“Istilah ini hidup di kalangan agama Buddha aliran Svabhavavak yang ada di Nepal. Aliran ini merupakan salah satu percabangan dari aliran Tantrayana yang tergolong Mahayana. Sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam aliran ini adalah Adi‐Buddha.
Paham ini kemudian juga menyebar ke Jawa, sehingga pengertian Adi‐Buddha dikenal pula dalam agama Buddha yang berkembang di Jawa pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Para ahli sekarang mengenal pengertian ini melalui karya tulis B.H. Hodgson. Ia adalah seorang peneliti yang banyak mengkaji hal keagamaan di Nepal.”
“Menurut paham ini seseorang dapat menyatu (moksa) dengan Adi‐Buddha atau Isvara melalui upaya yang dilakukannya dengan jalan bertapa (tapa) dan bersamadhi (dhyana).”
Vajrayana
Di dalam ajaran Vajrayana – yang berbasis Mahayana — memang dikenal adanya sosok Buddha primordial, yang sebenarnya adalah personifikasi kualitas terdalam dari batin kita di level Dharmakaya. Aliran Nyingma di Tibet yang muncul paling awal menyebutnya sebagai Samantabhadra. Sementara aliran Sarma yang muncul selanjutnya yakni Sakya, Kagyu, Jonang, dan Gelug menyebut sebagai Vajradhara. Sementara Buddha primordial dalam aliran Shingon atau tantra Jepang adalah Vairochana.
Jadi ada tidaknya konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha sebenarnya adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Itu jelas ada, meski bila ditelisik memiliki perbedaan konsep mendetail antar tiap aliran.
Sunyata
Kebenaran tertinggi di dalam agama Buddha sering juga disebut sebagai śūnyatā yang seringkali diterjemahkan sebagai kekosongan. Inilah yang oleh orang Jawa lalu disebut sebagai Kasunyatan, kebenaran tertinggi dalam filsafat Jawa.
Semua aliran mainstream Buddhis mengakui śūnyatā. Di kanon Pali ada Sutta Cula-suññata dan Sutta Maha-suññata yang membahas mengenai hal tersebut.
Di Mahayana ada Sutra Prajñāpāramitāhṛdaya dan banyak sutra lain yang memang membahas hal itu. Sementara di Vajrayana – yang berbasis Mahayana— śūnyatā tentunya juga diakui. Meski demikian, ada dua aliran shunyata yang berkembang dalam agama Buddha Tibet, yakni Rangtong dan Shentong.
Rangtong berarti “kosong dari sifat diri sendiri”. Ini adalah istilah filosofis dalam agama Buddha Tibet yang digunakan untuk menyebut tentang sifat śūnyatā atau “kekosongan”, yaitu bahwa semua fenomena kosong dari masa lalu dan/atau esensi yang tidak berubah atau “diri”, bahwa kekosongan ini bukanlah kenyataan absolut, melainkan hanya merupakan karakterisasi nominal dari fenomena. Rangtong ingin mengatakan bahwa di dalam realita yang absolut, tiada yang absolut.
Hal ini terkait dengan pandangan prasangika, yang berpendapat bahwa tidak ada bentuk penalaran silogisme yang seharusnya digunakan untuk memperdebatkan gagasan keberadaan yang inheren, namun hanya argumen yang menunjukkan implikasi logis dan absurditas posisi berdasarkan eksistensi yang melekat. Pandangan ini merupakan tafsir utama Madhyamaka dari Gelugpa, aliran Buddhisme Vajrayana yang didirikan oleh Lama Tsongkhapa.
Sementara Shentong yang secara harfiah berarti “kekosongan lain” adalah pandangan minoritas di dalam Madhyamaka Tibet. Ini artinya śūnyatā menyetujui kenyataan relatif kosong dari sifat diri sendiri, namun menyatakan bahwa kenyataan absolut itu sendiri tidak kosong dan benar-benar ada. Realitas absolut ini digambarkan dengan istilah positif, sehingga mirip dengan kebenaran tertinggi dalam konsep Hindu.
Shentong disistematisasikan dan diartikulasikan oleh Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-1361), seorang lama dari aliran Jonang, yang identik dengan praktik Tantra Kalachakra. Dalam sejarahnya, pandangan Shentong digilas oleh aliran Gelug yang dominan selama beberapa ratus tahun sejak Dalai Lama kelima, karena alasan politis dan doktrin. Pada tahun 1658, penguasa Gelug juga melarang aliran Jonang karena alasan politik, dan mengubah biarawan dan biara aliran itu menjadi Gelug. Ajaran dan kitab-kitab shentong dilarang, sehingga membuat posisi rangtong sangat dominan dalam corak agama Buddha Tibet dan aliran Jonang nyaris musnah.
Shentong
Namun pada abad ke-19 pandangan Shentong bangkit kembali, dan berlanjut dengan gerakan Rimé (non sektarian). Saat ini pandangan Shentong hadir lagi dan merasuk terutama di aliran Nyingma dan Kagyu.
Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa master abad kesebelas yang bernama Yumo Mikyo Dorje– siswa pandita asal Kashmir bernama Somanatha — adalah orang Tibet pertama yang mengartikulasikan pandangan shentong, setelah pengalamannya melakukan retret Kalachakra secara intensif.
Shentong lalu disistematisasikan oleh Dolpopa Sherab Gyaltsen yang awalnya adalah biksu aliran Sakya, yang terlahir di keluarga praktisi Nyingma, namun akhirnya bergabung dengan aliran Jonang.
Tahun 1321 Dolpopa mengunjungi Biara Tsurphu untuk pertama kalinya, dan melakukan diskusi ekstensif dengan Karmapa Ketiga Rangjung Dorje (1284-1339) tentang masalah doktrinal. Tampaknya Karmapa mempengaruhi perkembangan beberapa pandangan Dolpopa, termasuk metode shentongnya.
Seperti yang diramalkan Karmapa Rangjung Dorje, Dolpopa lalu mempraktikkan Kalachakra secara intensif, dan akhirnya merealisasi pandangan shentong.
Ia memperkokoh pandangannya ini dengan mengutip kitab Mahāyāna Sūtra Mahāparinirvāṇa, Sūtra Aṅgulimālīya dan Sātra Śrīmālādevī Siṃhanāda.
Dolpopa menyebut bahwa Buddha atau diri sejati yang ada di dalam masing-masing pribadi sebagai kebenaran aktual, tidak dikondisikan atau dihasilkan oleh proses sebab-akibat temporal.
Interpretasi
Interpretasi Shentong tentang doktrin tathāgatagarbha adalah bahwa Buddha di dalam semua makhluk adalah sifat-sifat yang tidak berubah, permanen, tidak terkondisi. Buddha adalah kualitas kebahagiaan, welas asih, kebijaksanaan, kekuatan, dan sebagainya yang dianggap sebagai sesuatu yang sesungguhnya terus ada permanen dan tak terbatas, walau tertutupi oleh keserakahan, kemarahan, dan kebotohan batin manusia.
Dia menegaskan bahwa kebenaran tertinggi, yang disebut oleh istilah seperti tathāgatagarbha (Esensi Buddha), dharmadhātu (Dimensi Kebenaran), dan dharmakāya (Tubuh Kebenaran), adalah keadaan permanen atau kekal. Menurutnya, semuanya berkaitan dengan ranah Nirvana, dan merupakan satu dengan sifat Buddha. Menurut Dolpopa, yang diutarakannya ini bukan sekadar pandangan intelektual, tapi pengalaman langsung tentang kebahagiaan dan realitas tertinggi yang telah dialaminya.
Karena itulah ia mendapat julukan Buddha dari Dolpo, seseorang yang sudah merealisasi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sumber pustaka:
Dolpopa Sherab Gyaltshen (2006). Mountain doctrine: Tibet’s fundamental treatise on other-emptiness and the Buddha-matrix. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.
Ensiklopedi Nasional Indonesia (1988). Jakarta: Cipta Adi Pustaka
Stearns, Cyrus (2010). The Buddha from Dölpo: a study of the life and thought of the Tibetan master Dölpopa Sherab Gyaltsen. Ithaca, NY: Snow Lion Publications.
Thera, Nyanaponika. “Buddhism and the God-idea”. The Vision of the Dhamma. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society. (accesstoinsight.org)
*Penulis, seorang jurnalis di Jogja. Dapat dijumpai di facebook, @deniclassic