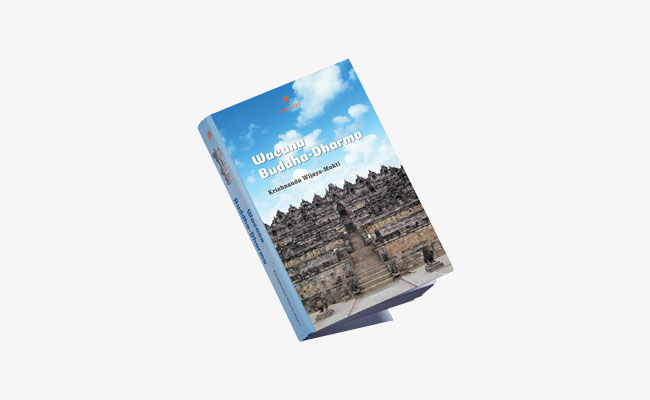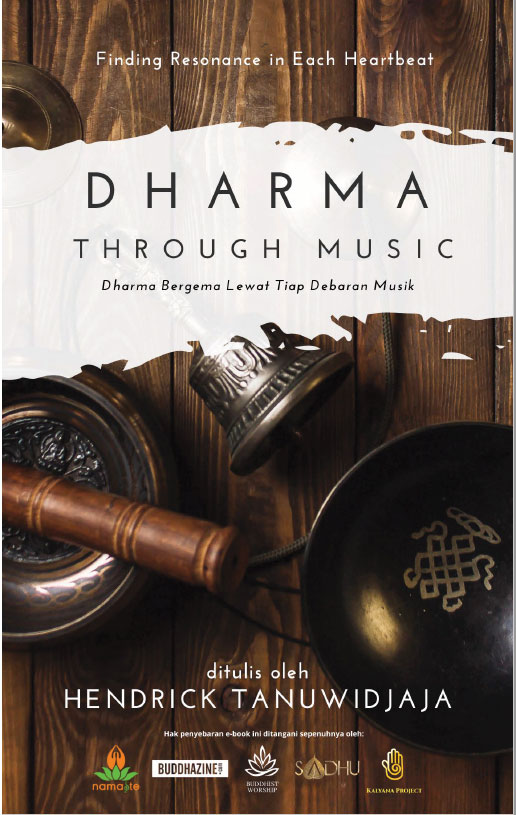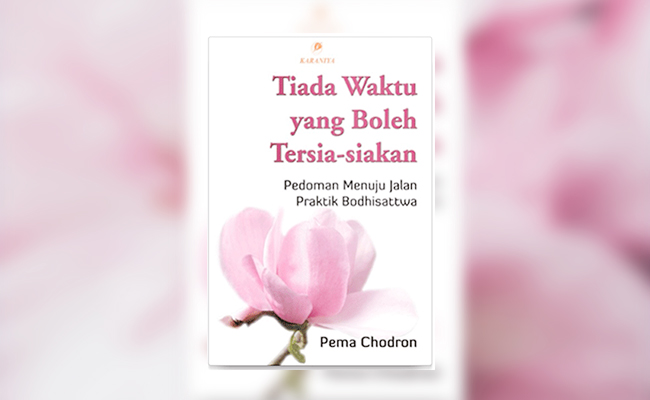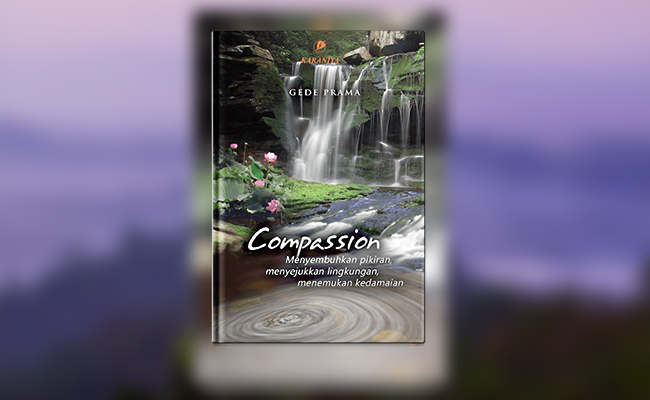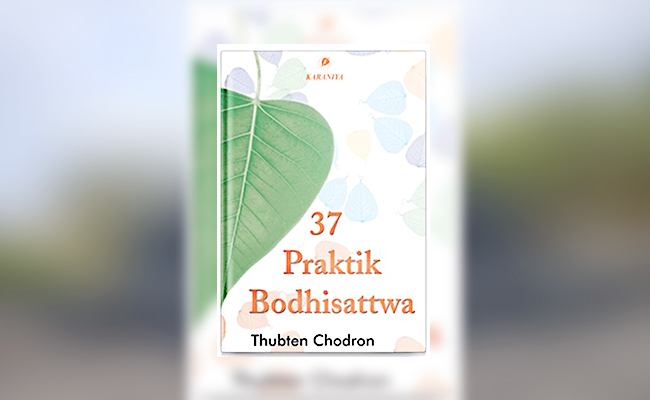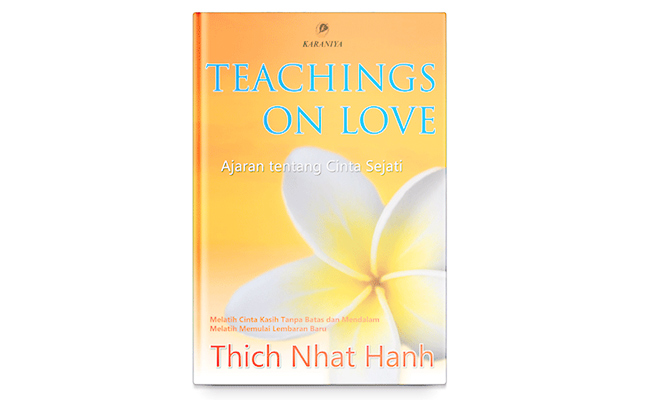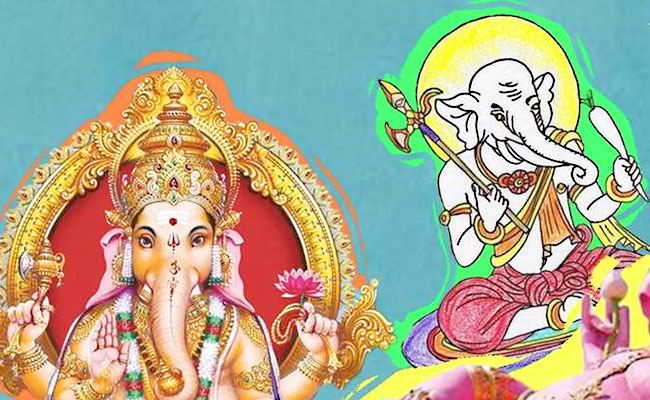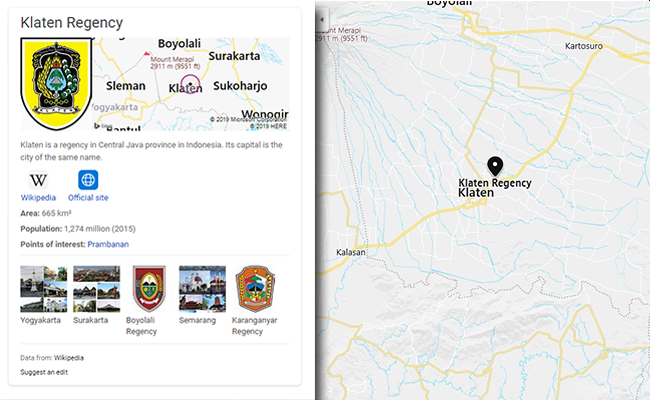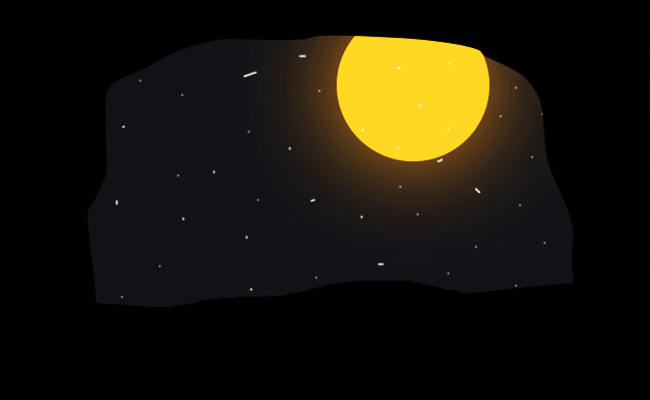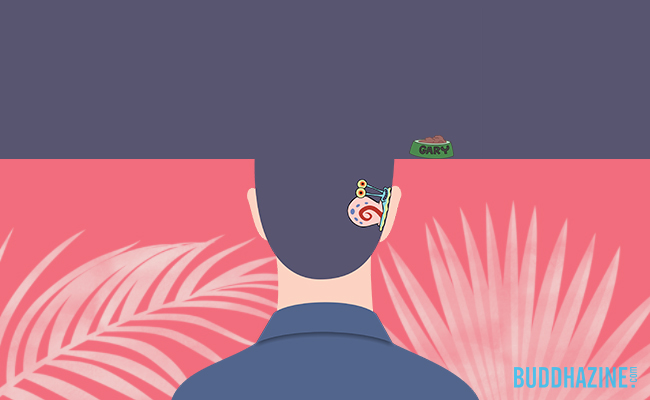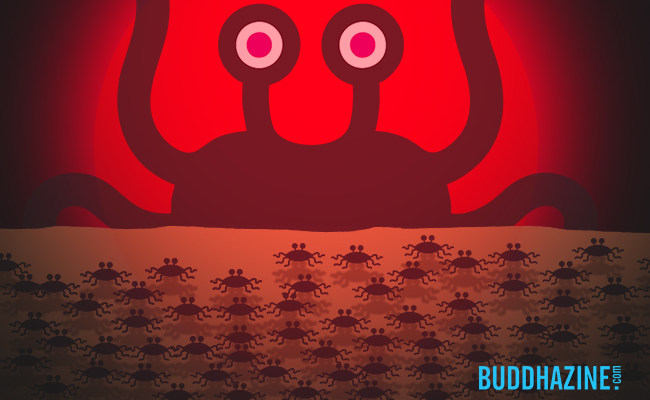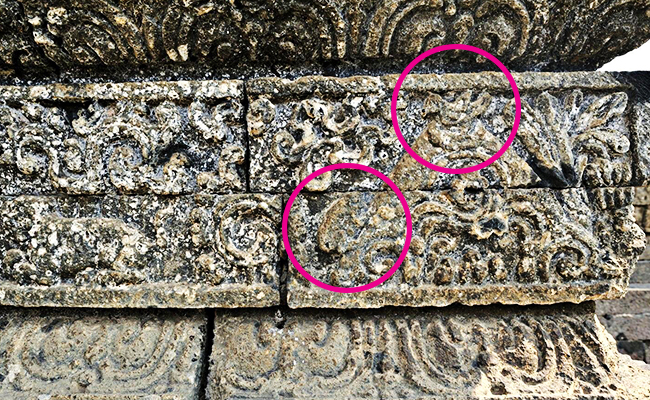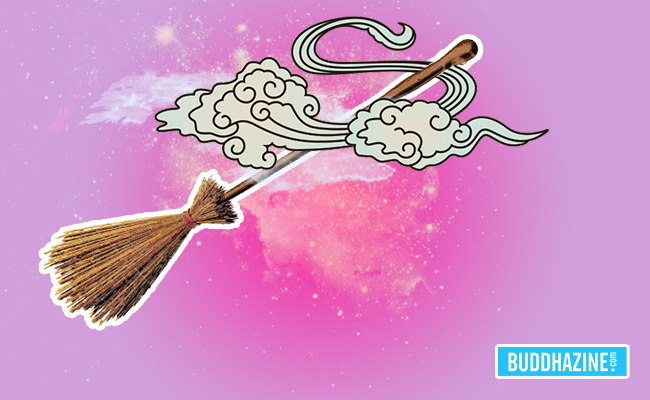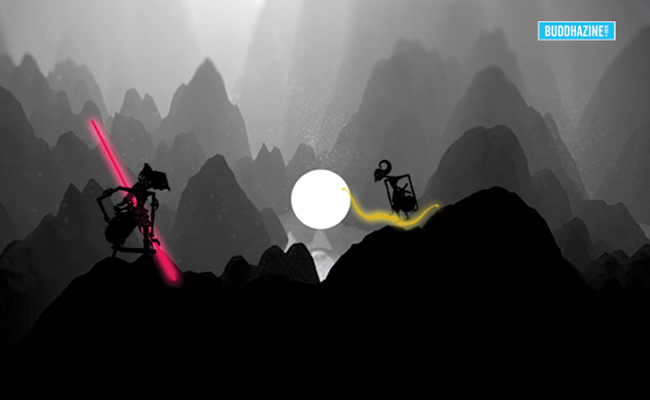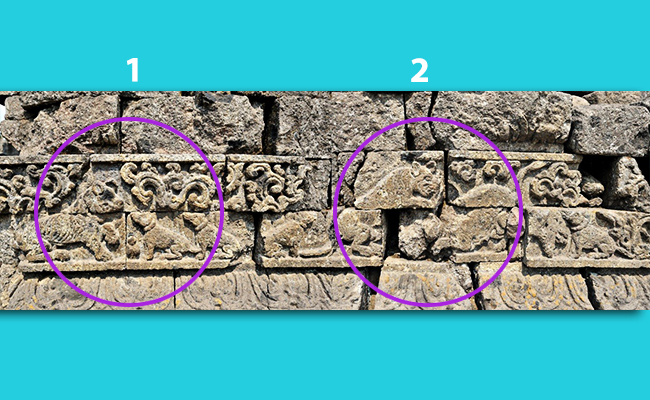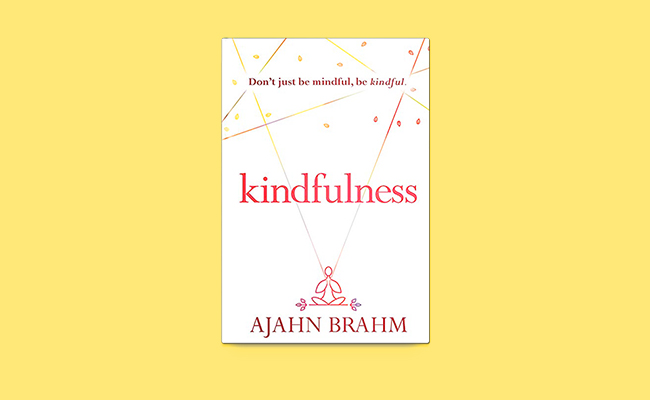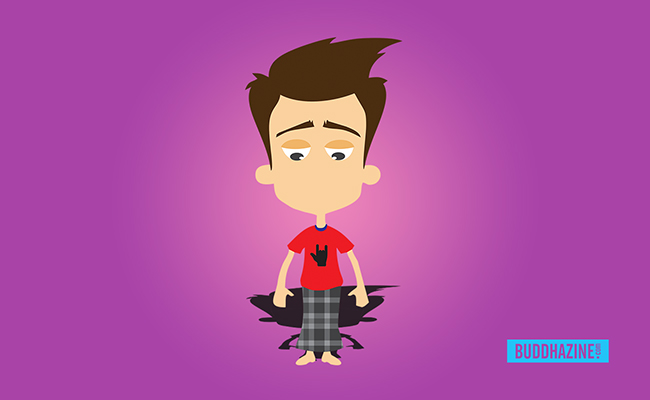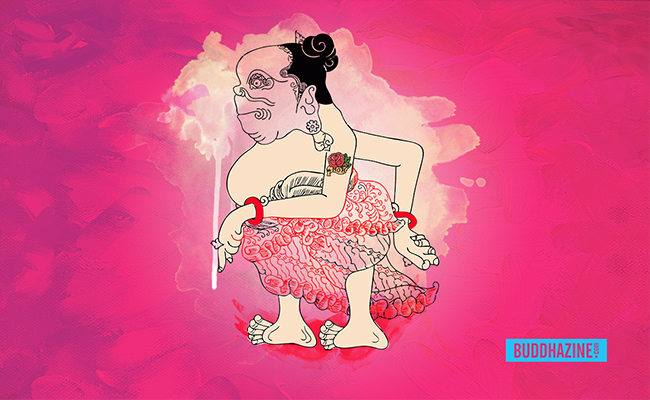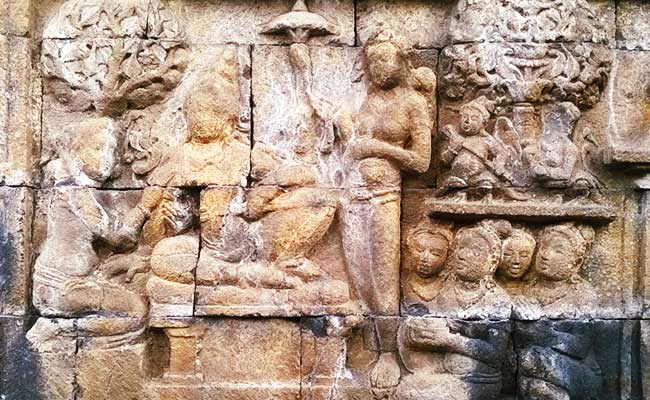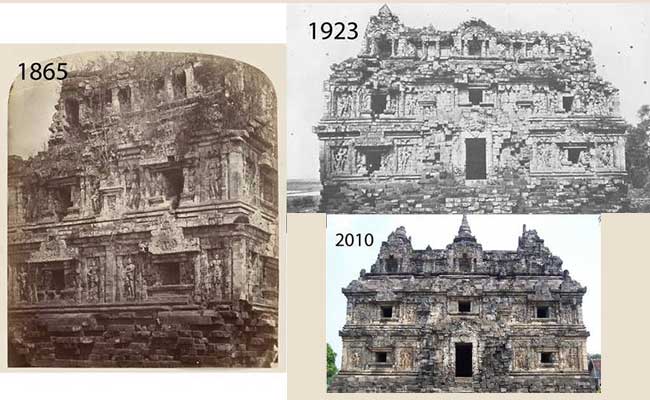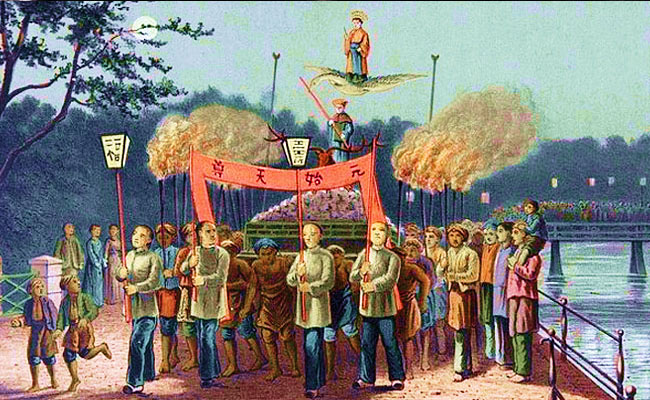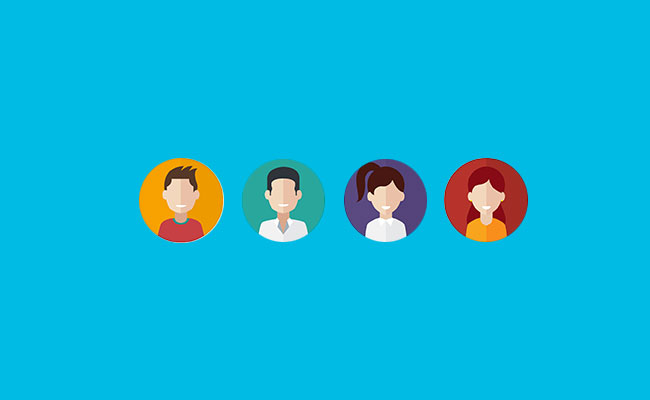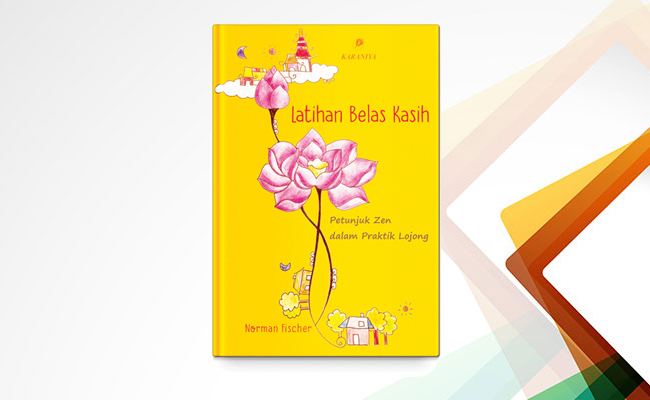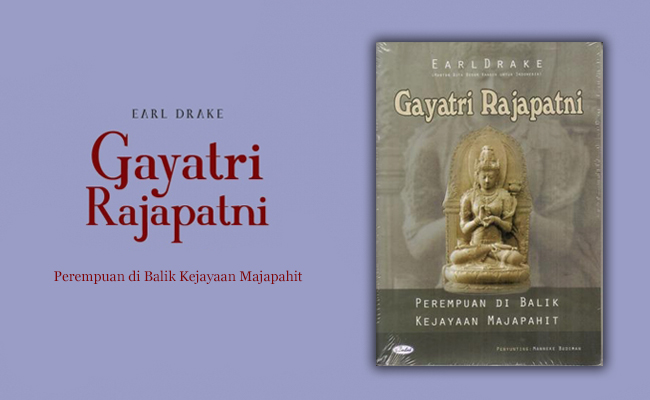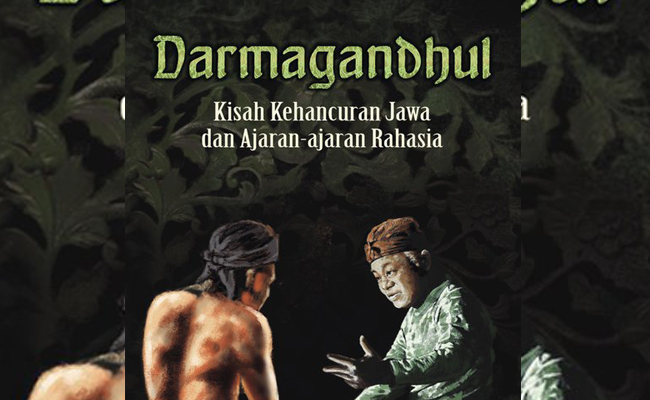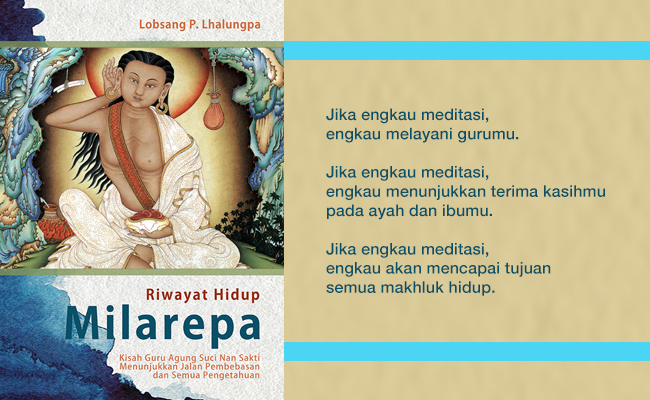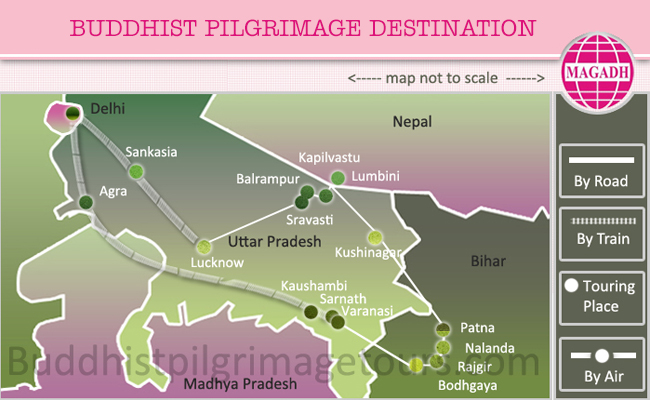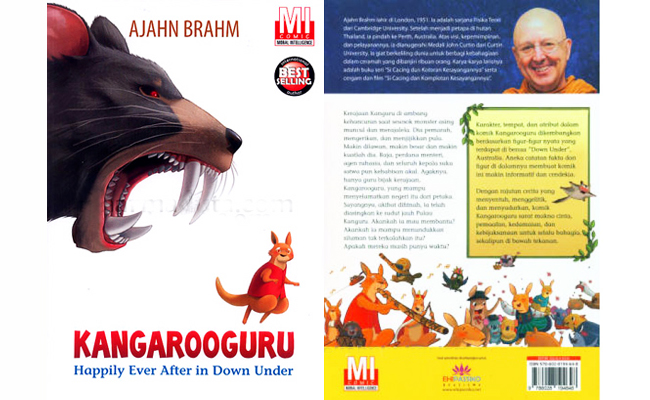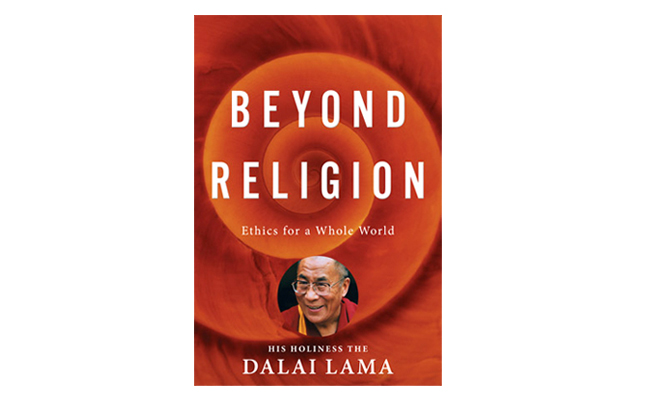Terentang Hulu adalah salah satu nama desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak. Untuk sampai di Kecamatan Terentang, dari dermaga Sungai Durian (dekat Bandara Internasional Supadio), jarak yang harus ditempuh berkisar 1,5 jam menggunakan speed boat.
Selain melalui jalur air, kabarnya desa ini juga dapat dituju lewat darat menggunakan sepeda motor, dengan estimasi waktu yang kurang lebih sama. Saya belum pernah menggunakan akses darat dan jika diminta memilih, saya akan tetap memilih melintasi aliran sungai-sungai Pontianak.
Kesan pertama saya mengunjungi tempat ini adalah pedalaman, hanya karena di sana tidak ada gedung-gedung beton menjulang kecuali sarang walet milik taipan-taipan luar, air sungai yang keruh, dan hilir mudik kapal klotok pengangkut buah sawit, lahan gambut, dan belantara karet dan sawit. Di Terentang Hulu tidak ada pula subsidi listrik. Dalam beberapa aspek desa ini memenuhi standar desa tertinggal.

Tidak berarti bahwa desa ini gelap gulita dan menyeramkan ketika malam. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di desa ini, sejak 1965 hingga sekarang, belum teraliri listrik. Meski demikian warga setempat tetap memiliki penerangan masing-masing ketika malam hari. Mereka menggunakan genset atau tenaga surya, khususnya bagi keluarga yang cukup mampu.
Pada tahun 2017 lalu, Lumir Inc, sebuah perusahaan di Korea Selatan, yang bekerjasama dengan Korea Trade-Investment Agency (KOTRA) telah menyelenggarakan proyek CSR, yaitu pendistribusian 100 lampu ‘Lumir K’ ke 100 rumah tangga di Terentang Hulu. Ini kabar bahagia, tentu saja.
Mengenai ketiadaan lisrik di Terentang Hulu, Pak Acong, seorang warga lawan bincang saya mengatakan, “Indonesia sudah merdeka, tetapi Terentang Hulu belum.” Ini terdengar lucu. Seakan-akan Terentang Hulu berada di bagian entah mana, atau di luar Indonesia. Itu wajar, saya pikir. Sebuah ungkapan kekecewaan dari seseorang yang mewakili sekelompok warga setempat.
Indonesia mungkin sudah lama merdeka dari jajahan bangsa asing dan belum lama ini merayakan harinya jadi tersebut, tetapi bagi mereka, warga Terentang Hulu, wajah dari kolonialisme bukan lagi tindakan tambung dan lalim dari para penjajah melainkan menjelma ketidakadilan dari pemerintah. Mereka selalu merasa dianaktirikan sejak dari zaman Soeharto.
Dibandingkan desa-desa lain, khususnya tempat transmigran bermukim, Terentang Hulu masih tertinggal dalam hal infrastruktur: listrik, salah satu contohnya. Hal lainnya adalah akses jalan. Dua desa trans di sisi Terentang Hulu, Sungai Dungun dan Radak Baru, sudah menikmati penerangan distribusi listrik.
Tetapi alih-alih menyalahkan pihak mana pun, alasan ketiadaan listrik di desa ini cukup terbilang masuk akal. Saya menduga dan menanyakan kemungkinan bahwa tidak/belum diperhatikannya Terentang Hulu oleh pemerintah perihal listrik adalah karena jarak antara satu rumah warga ke rumah lainnya yang cukup berjauhan. Warga trans di desa-desa tetangganya, misalnya, memiliki (dan memang diatur) pola permukiman yang mengumpul.
Pola ini, menurut Paul H. Landis, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika,adalah The Farum Village Type, yang mana warganya berkumpul di suatu tempat yang di sekelilingnya terdapat lahan-lahan garapan mereka. Dengan pola yang menyatu seperti ini otomatis pengaturan penyaluran listrik akan sangat mudah dan barangkali bisa menghemat anggaran.
Sedangkan warga Terentang Hulu, kira-kira memiliki pola The Pure Isolated Type, yang mana penduduknya berpencar-pencar, menempati lahan masing-masing. Tipe ini juga tidak sepenuhnya benar berlaku untuk warga di desa Terentang Hulu. Dengan bukti di sepanjang tepian sungai menuju wihara dan terutama di sekitaran kantor desa setempat, rumah-rumah warga berjejer berdekatan. Entahlah.
Pembinaan umat Buddha di Terentang Hulu
Awal bulan Agustus kemarin, tanggal 2–5, saya mengunjungi Terentang Hulu untuk kedua kalinya. Hanya tiga malam. Waktu yang singkat ini setidaknya cukup untuk mengenal lebih dekat dengan umat Buddha, khususnya generasi Buddhis di sana.
Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada Mei, saya bersama rombongan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI) Pontianak, yang sebagian besar pertama kali pergi ke Terentang, berkunjung untuk melakukan baksos dan sekaligus perayaan Waisak di sana.
Rombongan juga pernah datang pada tahun 2018, persis pada bulan dan tujuan yang sama yakni merayakan Waisak. Bhante Uggaseno, yang saat itu turut hadir, melakukan wisudhi upasaka dan uupasika kepada 55 orang umat. Berdasarkan catatan sipil jumlah umat Buddha di Terentang Hulu adalah sebanyak 512 jiwa.

Kali ini saya berangkat seorang diri, sore hari, menaiki speed angkutan umum. Batas tujuan akhir angkutan umum seperti ini adalah Sungai Radak 1, desa tetangga dan kira-kira setengah jam dari Terentang Hulu, dengan merogoh kocek 60.000 sekali jalan. Harga yang terbilang murah bila dibandingkan harus menyewa speed. Sebagai tambahan informasi mengenai lokasi, desa dengan nama Radak di Kecamatan Terentang ada 3 yakni, Radak 1, Radak 2, dan yang belum lama memekarkan diri, Radak Baru.
Di perjalanan saya bersebelahan dan bebincang dengan seorang lelaki paruh baya yang berasal dari Banyuwangi. Dia seorang warga trans, mengadu nasib di Pontianak sejak tujuh tahun yang lalu. Awalnya dia sanssi untuk menegur karena mengira saya seorang perempuan, sampai akhirnya kami berbincang banyak hal. Tentang kelapa sawit. Tentang sejarah. Tentang kehidupan.
Saya ingin tahu banyak bagaimana kehidupan rantau mereka di sana. Dia justru bertanya lebih banyak tentang kehidupan seorang bhikkhu. Boleh jadi memang atribut yang dikenakan oleh seorang bhikkhu memunculkan banyak tanda tanya bagi kebanyakan orang yang asing dengan agama Buddha.
Speed yang saya tumpangi sampai di pangakalan tujuan akhir di Radak 1 pada pukul 16.30 WIB. Saya dijemput menggunakan sepeda motor oleh Lili Candra Gunawan, putra bungsu dari Bu Wiharti, guru Sekolah Minggu. Dari pangkalan sebenarnya juga bisa melalui jalur air menuju kediaman Lili, tetapi karena sore hari air sungai surut, motor air (perahu motor) tidak bisa digunakan laju sehingga dipastikan akan sampai di rumah malam hari.
Alternatifnya adalah melalui darat, melewati permukiman warga dan menembus belantara kelapa sawit. Malam pertama, saya menginap di rumah Lili, karena wihara belum memiliki kuti dan tidak ada penerangan. Saya mendapati banyak lemparan senyum dari warga-warga sekitar selama di perjalanan di atas motor. Sebagai seorang pendatang baru, senyuman dari orang-orang tempat kita baru menginjakkan kaki itu amat menyenangkan, sangat menenangkan. Penerimaan adalah satu hal yang menyenangkan di dunia.
Sekolah Minggu Buddha (SMB) Dhammasakkacca
Anak-anak Sekolah Minggu di Terentang Hulu mulai mendapat bimbingan secara intensif pada tahun 2013. Adalah Bu Wiharti, seorang Kepala Dusun dan guru honorer di sekolah dasar negeri setempat, yang sudi meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya mengabdikan diri mengajar anak-anak.

Tahun itu Wihara Dhammasakkacca belum berdiri, sehingga proses belajar dilangsungkan di rumah Bu Wiharti sendiri. Dua tahun kemudian, 2015, Wihara Dhammasakkacca mulai dibangun. Pembangunan wihara ini tidak terlepas dari perhatian dan harapan Penyelenggara Bimas Buddha Kab. Kubu Raya yang pernah berkunjung. Gayung bersambut, harapan baik tersebut direspons baik pula oleh Bu Wiharti dan kedua kakak kandungnya, Pak Sunandar dan Pak Purwoto.
Mereka menghibahkan tanah seluas kurang lebih 500 meter ketika itu. Wihara kini berdiri persis di depan kediaman Pak Sunandar, hanya terpisah oleh jalan. Pak Purwoto sendiri adalah Kepala Desa di Terentang Hulu. Baru-baru ini, mereka kembali menambah luas hibah tanah (ke belakang) untuk rencana pembangunan kuti, perampungan ruang Sekolah Minggu, dan kamar mandi jika memiliki dana.
Jumlah anak-anak sekolah Minggu (SMB) di Wihara Dhammasakkacca, kata Bu Wiharti, lebih dari 50 anak. Lima puluh itu bukan jumlah yang sedikit. Ir. Soekarno hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Jika diberikan kepada beliau, mungkin ia akan mengembalikan 40 sisanya. Sembari duduk santai di kursi goyangnya, dengan satu tangan memegang cerutu dan tangan lainnya menunjuk ke arah gerbang, mengatakan, “Sana bawa pulang 40 pemuda sisanya ini.
Aku hanya butuh sepuluh pemuda untuk mengguncangkan dunia!” Siapa tahu, kan? Jumlah itu adalah kuantitas nyata bagi masa depan, bagi kelangsungan agama Buddha. Jika di sebuah wihara tidak terdapat anak-anak muda, dapat dipastikan di sana tidak ada masa depan. Begitu juga dengan agama Buddha dan keberadaan generasi umatnya sebagai penerus.

Anak-anak ini terdiri dari SD, SMP, dan beberapa SMA. Mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar adalah murid Bu Wiharti sendiri, dan hanya pada jenjang inilah mereka mendapatkan pelajaran agama di bangku sekolah. Sedangkan yang SMP dan SMA, mereka tidak mendapatkan materi pendidikan agama Buddha, dikarenakan tidak ada tenaga pengajar.
Alhasil mereka harus mengikuti kelas agama lain sebagai formalitas pemenuhan kolom nilai agama di raport. Alasan inilah yang mendasari Bu Wiharti memilih untuk terus mengajar dan tanpa henti mendorong anak-anak datang ke wihara setiap hari Minggu. Semangat dan kasih sayang yang tunjukkan oleh Bu Wiharti pada akhirnya membuahkan antusiasme pada anak-anak didiknya, generasi Buddhis di Terentang Hulu. Guru hebat seyogianya melahirkan murid yang hebat pula.
Setiap hari Minggu mereka akan berkumpul di tepian sungai, di atas pangkalan kayu menunggu Bu Wiharti melintas mengemudikan motor air menuju wihara. Wihara memiliki inventaris motor air yang didanakan donator untuk keperluan wihara. Ukurannya sedang, cukup untuk menampung belasan anak.
Bu Wiharti pernah bercerita bahwa anak-anak ini tidak hanya menumpang ketika ke wihara saja tetapi juga saat berangkat ke sekolah. Ketika bertolak, Bu Wiharti juga akan mengantarkan mereka kambali sampai di pangkalan masing-masing. Mereka memiliki semangat yang besar untuk belajar Dhamma. Saya menyaksikannya dan tidak ragu mengatakan bahwa mereka memang memiliki semangat yang besar. Tetapi semangat saja cukup.
Saat ini saya berdomisili di Singkawang dan membantu pembinaan umat Buddha di Kalimantan Barat.
=================
Ayo Bantu Buddhazine
Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara